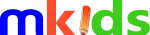Tin..tiiin!
Belum juga tiba di halaman rumah, sebuah mobil bak terbuka membunyikan klaksonnya berkali-kali.
Leha segera beranjak dari tempat duduk, menyudahi sarapan paginya bersama ibu. Ia menyambar tas kecil berisi botol minum dan gawai. Tangannya menyenggol gelas di samping ibu. Hampir saja gelas itu jatuh kalau ibu tidak segera memegangnya. Beruntung, hanya sedikit air yang tumpah di atas taplak meja. Ibu menggelengkan kepala melihat tingkah putri semata wayangnya. Selalu saja begitu, batin ibu.
“Itu Bapak, Bu!” pekik Leha.
“Kalian sudah siap?” tanya Bapak, “Ayo cepat, balai desa mulai ramai, lo!”
Leha segera berlari dan dengan sigap menaiki bak mobil. Gerakannya sangat cepat dan lincah. Persis seperti pemain parkur profesional. Beberapa orang yang berada di bagian belakang mobil itu tersenyum, sebagian lagi hanya menghela napas. Cemas dengan polah anak tunggal kepala dusun mereka. Leha menyalami dan menyapa mereka satu per satu.
Tak lama, ibu segera menyusul. Mobil pun melaju perlahan. Jalan desa yang berkelok, seakan membelah hamparan ladang tembakau milik warga. Dua gunung kembar Sindoro Sumbing terlihat gagah, seolah menjadi ujung dari pemandangan indah ini.
Jalanan desa tampak meriah. Umbul-umbul dengan berbagai warna menghiasi setiap jengkal jalan trasah. Ada ritual wiwit mbako panen kopi di lapangan desa. Dalam bahasa Jawa, wiwit artinya mulai. Ritual ini untuk menandai dimulainya panen tembakau yang bersamaan dengan berakhirnya panen kopi. Jika petani tembakau baru memulai panen pertama, maka petani kopi sudah memasuki akhir masa panen.
Di balai desa, para warga sudah berkerumun. Mereka mengenakan pakaian tradisional adat Jawa, lengkap dengan blangkon bagi laki-laki dan sanggul bagi perempuan. Tampak beberapa gunungan berisi hasil bumi. Ada lombok, kacang panjang, terong, tomat, mentimun, serta buah-buahan. Gunungan sebagai simbol kemakmuran dan keberkahan, akan diperebutkan oleh warga sebagai penutup rangkaian acara.
Leha melirik deretan nasi tumpeng dengan ayam ingkung. Nasi dihias di atas sebuah tampah yang cukup besar. Bermacam lauk-pauk pendamping seperti sambal goreng ati ampela, kering kentang dan kacang tanah, perkedel kentang, urap sayur, dan irisan telur dadar, semua tersaji lengkap. Meski baru saja menghabiskan sarapannya, beberapa kali Leha menelan ludah. Hidangan diatas anyaman bambu itu memang terlihat sangat menggiurkan.
“Leha, ayo cepat kemari!”
Dari balik kerumunan muncul seorang perempuan berkebaya hitam dengan jarik batik dan rambut bersanggul.
“Segera pakai ini lalu cepat berdandan! Duh, kenapa kamu tidak datang lebih awal? Lihat itu, teman-teman sudah lama menunggu!” Perempuan itu nyerocos.
“Maaf Bu,” sahut Leha. Perempuan itu bernama Bu Erni, sang pelatih tari.
“Yowis, yowis. Yang penting kamu sudah ada di sini.”
Bu Erni segera pergi setelah menyerahkan kostum. Leha masih memperhatikan Bu Erni, kepalanya tampak menjulur dan menoleh kesana kemari. Melihat gelagatnya, mungkin ada beberapa anak yang belum datang.
“Ha, ayo cepat!” seru seseorang dari ruang ganti.
Leha segera masuk dan langsung mengenakan kostumnya. Di ruangan itu, berjejer anak-anak penari Jathilan dan Topeng Ireng. Sebagian mereka sudah siap tampil, namun ada beberapa yang masih dirias.
“Wah, ayune!” Leha memperhatikan para penari Topeng Ireng,
Gadis-gadis remaja itu memang kelihatan sangat cantik. Sebenarnya, Leha ingin sekali menari Topeng Ireng. Namun sayang, kali ini hanya remaja perempuan yang diminta Bu Erni untuk menarikannya.
Leha menyukai kostum mereka, apalagi hiasan kepalanya. Terbuat dari bulu warna-warni yang menyerupai mahkota suku Indian, hiasan kepala itu terlihat bagus dan meriah. Kostum bawahnya adalah rok rumbai-rumbai seperti suku Dayak. Alas kakinya berupa sepatu bot yang dilengkapi dengan gelang kelintingan. Saat digerakkan, bunyinya akan terdengar riuh gemerincing. Mata Leha menerawang, ia membayangkan dirinya mengenakan kostum tarian itu.
“Leha, giliranmu!” seruan juru rias membuyarkan lamunan Leha. Di saat bersamaan, Bu Erni datang dengan tergopoh-gopoh. Wajahnya terlihat panik.
“Aduh, gawat! Wawan tidak bisa datang hari ini. Kata ibunya, dia sakit,” kata Bu Erni dengan napas terengah-engah.
“Leha, kamu ganti peran jadi warok ya, Nduk. Kamu kan sudah sering njathil,”
“Saya, Bu?” Leha terbelalak sembari menunjuk hidungnya sendiri.
“Iya toh, siapa lagi? Dedegmu pas untuk menggantikan Wawan! ” kata Bu Erni mantap.
Seketika raut muka Leha berubah masam. Selain belum pernah menjadi warok, dia pun tidak menyukai riasannya. Seorang warok akan dirias dengan wajah berwarna merah, lengkap dengan kumis dan brewok yang lebat supaya terkesan garang. Sepanjang tarian, mata penari warok akan melotot untuk mendapatkan kesan tersebut. Leha mencoba mengelak. Namun, permintaan pelatih tari itu tak bisa ditolak.
Leha kembali menuju ruang ganti dan menukar kostumnya dengan baju serba hitam. Sarung bermotif kotak-kotak melilit bagian perutnya.
“Ada-ada saja, warok kok perempuan,” Leha masih menggerutu. Dia semakin sebal dengan riasan wajahnya yang tebal dan terasa gatal.
Alunan gending Jawa mengiringi arak-arakan gunungan dan tumpeng menuju lapangan desa. Panggung besar dengan hiasan rigen-rigen tembakau berdiri kokoh menyambut kedatangan para warga. Ritual dibuka dengan pertunjukan tarian Jathilan oleh anak-anak kelas lima sekolah dasar. Saatnya Leha beraksi. Tangannya mulai basah. Denyut jantungnya bergerak makin cepat.
Saat gendhing jathilan mulai terdengar, Leha menarik dapas dalam-dalam dan berjalan ke tengah lapangan, “Aku pasti bisa!”
Dengan membawa kuda kepang dan pecut, Leha bergerak lincah memperagakan seorang prajurit berkuda yang gagah perkasa.
Semua berjalan lancar, teman-teman penari yang lain mengikuti gerakan Leha. Saat matahari mulai tinggi, tubuh Leha mulai berkeringat. Dia merasakan wajahnya semakin gatal. Ditahannya rasa itu dengan sekuat tenaga. Leha menunduk, menghindari terpaan sinar matahari.
Dari kejauhan, Bu Erni terlihat menganggukkan kepala. Tangan kanannya mengepal “Semangat!”
Leha terlihat gugup. Namun, saat namanya dielukan, Leha menjadi mantap dan percaya diri. Kegugupan yang dirasakannya hilang bersama riuh tepuk tangan penonton. Ia juga lupa dengan gatal di wajahnya. Leha benar-benar menjadi bintang lapangan. Dialah warok cilik perempuan pertama di desa.
Tarian demi tarian sudah ditampilkan. Tanpa terasa, ritual telah mencapai acara puncak. Saatnya tetua desa memimpin doa. Sebentar lagi, pemotongan tumpeng akan dilakukan dan dilanjutkan dengan makan bersama.
“Nah, ini dia!” Leha melonjak girang.
Seluruh warga desa duduk berjajar menurut kelompok dusun masing-masing. Berlembar-lembar daun pisang berada di tengah mereka yang duduk saling berhadapan. Berbagai lauk dan nasi tumpeng tersaji di atasnya. Satu set nasi tumpeng akan dinikmati oleh lima hingga enam orang warga. Leha sudah tidak sabar untuk menikmati ingkung yang dilihatnya pagi tadi.
“Ini untukmu, warok cilik,” kata Bu Erni seraya membawa satu baki nasi tumpeng. Wah, dengan semangat Leha mulai melahap hidangannya. Hmm, nikmat!
-o0o-
Cerpen ini diikutsertakan dalam Lomba Cipta Cerpen Anak Paberland 2024
Glosarium
Parkur: olahraga melintasi rintangan dengan berlari, memanjat, atau melompat dengan cepat dan efisien, biasanya dilakukan di lingkungan sekitar gedung.
Jalan trasah: jalan berbahan batu yang tersusun dan tertata rapi.
Nduk: dari kata genduk, artinya panggilan sayang untuk anak perempuan Jawa.
Njathil: menari Jathilan, disebut juga dengan Kuda Lumping atau Kuda Kepang.
Blangkon: penutup kepala adat Jawa bagi kaum laki-laki.
Ingkung: ayam yang dimasak dengan bumbu yang sangat lengkap ditambah dengan kuah santan kental.
Tampah: perabot rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk bulat yang digunakan untuk menampi (membersihkan) beras.
Yowis: dalam bahasa Jawa artinya ya sudah.
Dedeg: tinggi badan atau postur tubuh.
Rigen: lembaran anyaman bambu berbentuk segi empat panjang yang digunakan petani untuk menjemur tembakau.