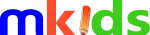Pada suatu hari di sebuah rumah kecil dekat pantai, ada seorang anak bernama Joan. Joan hidup bersama Oma, Papa, Mama, dan satu Kakak laki-laki yang biasanya disapa Gil. Papa dari Joan adalah seorang nelayan, sedangkan Mamanya berjualan ikan di pasar. Mereka hidup sebatang kara tetapi selalu diajarkan bersyukur.
Pagi telah tiba, ini waktunya bagi Joan dan Gil berangkat ke sekolah. Oma membuatkan singkong goreng dan teh gula sebagai menu sarapan tiap hari. Jikalau singkong di halaman rumah belum siap panen maka Oma akan menggoreng pisang sebagai gantinya. Beliau tidak senang melihat cucu-cucunya pergi dengan perut kosong.
“Joan, Gil.” Sapa salah satu teman sekelas Joan, Eben namanya. ‘Tunggu!” Teriak Joan dari dalam rumah tatkala buru-buru mengunyah sarapan. “Oma, Mama, Papa, kami berangkat ya.” Pamit Gil seraya mengenakan tas sekolah. “Sudah berdoa belum?” Tanya Mama memastikan. Baru juga Gil menginjak ambang pintu, dia kembali masuk ke dalam. “Hehe, lupa.” Ujarnya tersenyum kikuk.
“Sampai nanti, semua!”
Kali ini Gil dan Joan langsung meninggalkan rumah, mereka hendak menimba ilmu demi bekal masa depan. “Joan, Gil, ayo kita bolos!” Ajak Eben tiba-tiba. “Bosan tahu sekolah terus.” Sambungnya lagi. Joan menatap Kakak lelakinya penuh semangat, dalam hatinya dia mau sekali mengikuti ajakan Eben. “Saya tidak setuju, kita tetap harus berangkat sekolah.” Tolak Gil lalu melanjutkan perjalanan.
Bibir Joan cemberut, dia bingung akan pihak mana yang harus dia dengar. Alhasil anak itu malah diam tak bergeming dan sibuk berpikir. “Kak Gil, kita bolosnya satu kali ini saja. Tidak masuk sehari kan bukan masalah, besok kita hanya perlu berbohong kalau hari ini sakit.” Tutur Joan supaya Kakaknya terbujuk. Gil menoleh ke belakang, memandang Joan nan sudah berekspresi memelas.
“Joan, tadi sebelum ke sekolah kamu berdoa tidak?”
“Berdoa.”
“Kamu berdoa untuk bolos atau untuk belajar?”
Tidak mendengar jawaban apa-apa dari Joan setelah lama terdiam, Gil pun berucap, “Kalau mau bolos, bolos sendiri sana.” Lama makin lama, Gil terlihat menjauh. Joan masih ragu akan keputusan yang mau dia ambil. Di tengah keraguannya, Eben merangkul pundak Joan. “Tenang saja Joan, membolos tidak membuat kita masuk penjara kok.” “Tapi…” “Sudah, lebih baik kita memetik mangga. Itu buah kesukaanmu, kan?”
Eben membawa Joan ke kebun mangga yang lokasinya tak terlalu jauh dari sekolah. Di sana pohon-pohon sudah berbuah banyak, hal itu membuat Joan semakin mau memetiknya. “Eben, buah-buah di sini sudah banyak. Mengapa tidak dipetik oleh pemilik kebun?” Tanya Joan ketika menyaksikan temannya sudah memanjat pohon.
“Katanya sih, sudah disasi.”
“Memangnya sasi itu apa?”
“Lho, kamu tidak tahu? Itu budaya pelestarian lingkungan hidup dengan cara memberi larangan untuk mengambil suatu sumber daya alam, selama jangka waktu tertentu.” Jelas Eben sesuai apa yang ia tahu. “Lalu… Kenapa mangga-mangga ini mau kamu petik?” Tanya Joan lagi. “Mau saja, memangnya kenapa tidak boleh?”
“Tentu saja tidak boleh, budaya sasi itu melibatkan upacara adat dan doa. Jika berbuat hal yang salah maka kalian akan terkena musibah.” Timpal suara tak dikenal yang asalnya tidak jauh dari tempat Joan berpijak. “Hei, kamu, turun dari pohon.” Titah lelaki paruh baya yang adalah penjaga kebun itu dan dituruti oleh Eben. “Kalian berdua bukannya ke sekolah malah berniat curi mangga. Saya laporkan ya ke pihak sekolah.”
“Ja-jangan Om, saya akan dimarahi mama nanti.” Pinta Eben hendak menangis.
“Jangan adukan saya, Om. Saya hanya mengikuti usulan Eben.”
“Lho, kok kamu menyalahkan saya?”
“Lho, tadi kan kamu yang ajak!”
Kedua anak kelas 3 SD tersebut kini sibuk menyalahkan satu sama lain atas tindakan nan sudah mereka ambil. Akibatnya Sang Penjaga Kebun memutuskan supaya menyerahkan Eben serta Joan ke pihak sekolah daripada mereka sibuk berdebat. Orangtua masing-masing mereka dipanggil oleh guru BK, juga mendapat pesan supaya lain waktu kejadian ini tidak terulang.
Malamnya, Joan takut menuju meja makan tuk berkumpul dengan anggota keluarga yang lain. Dia cukup lelah mendengar omelan Mamanya sejak pagi tadi, bagaimana bila Sang Papa turut menegurnya? “Joan,” panggil Papa Joan cukup lantang. Anak lelaki yang dimaksud tidak punya pilihan lain kecuali mendatangi meja makan.
“Ya, Pa?” Sahut Joan.
“Mari ke sini, memangnya kamu mau melewatkan makan malam?”
Satu kursi kayu segera Joan tempati mengingat perutnya sudah keroncongan. Menu makan malam ini adalah ikan bakar, colo-colo (kecap bercampur tirisan lemon, garam, bawang, daun kemangi, dan tomat yang sudah dipotong kecil-kecil), sayur kangkung, nasi, dan jangan lupa satu tampa garam (tempat kecil/mangkuk berisikan garam dan cabe) yang terletak di tengah-tengah meja. “Gil, tadi kenapa tidak ke sekolah bersama adik?”
“Saya-“
“Pa, Kakak sudah mengajak saya. Saya saja yang menolak mendengar perkataan dia.”
“Oh, jadi sudah tahu cara membangkang ya.” Kata Papa seraya menimba nasi di piring masing-masing anaknya. “Joan, sekolah tidak menyenangkan ya? Apa mau berhenti sekolah saja?” Seketika semua orang terdiam. Tidak ada yang berani menjawab pertanyaan Sang Papa.
“Joan, Papa sedang bertanya. Kamu mau berhenti sekolah?”
“Tidak mau, Pa…”
Senyuman tipis pun terlukis pada wajah Papa. “Kamu dan Kakak harus bersekolah yang benar, bukan demi Oma, Mama atau Papa. Semua itu demi diri kalian di masa depan. Selama Papa dan Mama masih kuat, kalian pasti bisa sekolah. Asalkan kalian tidak main-main saat mengejar kesuksesan.”
“Jadi nakal itu wajar, Papa dulu juga nakal. Namun, Papa berharap kalian tidak menjadi seperti Papa. Katanya mau jadi abdi negara? Harus disiplin, dong.” Ujar Papa lagi. Joan pun merasa bersalah. Kini dia sadar akan kesalahan yang ia lakukan. “Maaf, Pa. Saya janji lain waktu tidak akan bolos apalagi berniat mencuri hasil sasi lagi.”
“Janji, ya?
“Janji, Pa.”
Sesudah Joan berucap demikian, bunyi perutnya menggema dan didengar oleh seluruh ruangan. “Pft- hahaha. Kamu kenyang nasehat tapi masih lapar makanan ternyata,” ejek Gil membuat yang lain tertawa. “Ayo, sebelum makan kita satu di dalam doa.” Ajak Nenek kemudian mendoakan makan malam kepunyaan mereka.
Di sela-sela makan malam Gil bertanya kepada Sang Oma. “Oma, mengapa tampa garam harus ada di meja makan?” Oma pun menjawab, “Tampa garam itu melambangkan keutuhan, keharmonisan, kedamaian, dan kehadiran Tuhan di tengah keluarga. Tampa garam tidak bisa lepas dari meja makan karena keduanya punya keterikatan yang kuat, Gil.”
“Cabe dan garam sendiri menyimbolkan kehidupan keluarga yang mempunyai beragam rasa tetapi dapat dicicipi bersama-sama,” timpal Mama. “Oh… Seperti kalimat, “Ale rasa beta rasa (kamu rasa, saya juga merasakan) ya Ma?” Tanya Gil memastikan. “Eh, kok saya mendadak ingat Lagu Gandong; ya?” Sela Joan. “Saya kan ambil kalimatnya dari lagu itu, Joan.” Seluruh anggota keluarga pun menertawakan interaksi antara Joan dan Gil. Mereka melanjutkan makan malam dengan damai dan permai.
Selesai.
Cerpen ini diikutsertakan dalam lomba cipta cerpen anak PaberLand 2024.
Sumber gambar : Republikanews