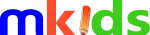Bab 12
Tari Kolosal Zaman Kerajaan
Keesokannya, Ayah mengajak Bunda dan Ajeng pulang ke rumah di Pekalongan. Di dalam mobil, Ajeng terus berceloteh, menceritakan keseruannya mengobrol dengan Kak Sandra.
“Kamu seneng banget, ya, Jeng, ketemu Kak Sandra?”
“Iya dong, Yah. Bahkan, Kak Sandra ngajak duet kalau kakiku sudah sembuh. Waaah … Ajeng udah nggak sabar,” ungkap Ajeng sambil bersorak kegirangan.
Ayah dan Bunda turut senang melihat kebahagiaan Ajeng. Bukan hanya Ajeng yang tak sabar saat-saat duet mereka, orang tuanya juga ingin cepat menyaksikan.
Lelah bercerita, Ajeng akhirnya terlelap di kursi belakang. Sementara Bunda duduk di depan, sembari menemani Ayah yang sedang mengemudi.
“Ajeng kelihatan seneng banget, ya, Yah. Lihat! Ajeng tidur sampai senyum-senyum sendiri,” ucap Bunda yang menoleh sekilas sambil terkikik.
Ayah pun langsung melirik ke kaca spion di tengah. Dia memandangi wajah Ajeng yang berseri-seri. Ayah ikut melengkungkan senyum. Sementara itu, Ajeng kembali bertemu Bufi di Negeri Impian.
“Halo, Ajeng. Senang bertemu kamu lagi. Oya, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, selalu diberi kesehatan, dan dikabulkan segala cita-citanya.” Bufi kemudian merangkul Ajeng.
“Aamiin, terima kasih, Bufi.” Ajeng terharu, ternyata Bufi tahu hari ulang tahunnya.
Sebagai hadiah, Bufi berniat mengajak Ajeng menyaksikan tari kolosal peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya yang unik, yaitu Tari Gending Sriwijaya.
Tak beberapa lama, mereka pun tiba di daerah yang terkenal dengan pempeknya. Ajeng pun sudah bisa menebak, tempat dia berada saat ini. Di mana lagi kalau bukan Palembang, Sumatera Selatan.
“Sudah sampai, Jeng.” Ajeng lantas membuka mata. “Kita cobain pempek dulu, yuk. Mumpung berada di tempat asalnya,” ajak Bufi.
Senyum mengembang di wajah Ajeng, membayangkan rasa cuko asem manis ditambah irisan mentimun yang diguyur di atas pempek. Seketika Ajeng menelan ludah.
“Wah, asyik! Kita ada di Palembang!” sorak Ajeng gembira. “Tapi, kita mau belajar tari apa, Bufi?”
“Coba tebak?”
Ajeng berpikir sekejap seraya mengetuk-ngetuk telunjuk di dahi. Kemudian, dia baru ingat beberapa nama tari tradisional yang ada di Palembang.
“Aku tahu, pasti Tari Tanggai?”
Bufi menggeleng cepat.
“Kalau gitu, Tari Sambut Silampari.”
“Bukan,” jawab Bufi singkat.
“Terus apa dong? Eehmm, Tari Tepak Keraton, ya?”
“Masih salah, yang bener Tari Gending Sriwijaya.”
“Tari kolosal?” gumamnya.
Ajeng baru pertama kali mendengar nama tarian itu. Dia sampai melongo sambil mengerutkan dahi. Bufi sontak tersenyum lebar, melihat keterkejutan Ajeng.
Sebelum mengajak sahabatnya menyaksikan Tari Gending Sriwijaya, Bufi membawa Ajeng ke kedai pempek terkenal di kota Palembang. Kedai cukup ramai pengunjung, tetapi tak berarti harus menunggu lama untuk menikmati pempek khas Palembang.
Ajeng yang begitu menyukai makanan dengan bahan tepung kanji dan ikan tenggiri itu, hingga mampu menghabiskan dua mangkuk sekaligus.
“Ah, sedapnya … kalau perutku masih muat, pasti aku mau nambah lagi.” Ajeng mengusap perutnya yang kini sedikit buncit.
Bufi pun tertawa dan bergeleng-geleng heran. “Bisa meletus nanti, kalau makan terlalu kenyang.”
Seusai menikmati pempek, Bufi mengajaknya ke sebuah acara pertunjukan budaya. Di sana Tari Gending Sriwijaya dijadikan tari pembuka. Makna dari tarian itu sendiri sebagai tari penyambutan tamu. Tari ini melukiskan kegembiraan gadis-gadis Palembang saat menerima tamu yang diagungkan.
“Sekarang kamu perhatikan, ya, Jeng. Awal-awal para penari naik ke panggung.”
Ajeng pun memperhatikan dengan seksama. Ketika sembilan penari perempuan keluar dan dikawal oleh dua lelaki membawa tombak dan payung. Sembilan penari itu mengenakan pakaian adat aesan gede, lengkap dengan aksesoris berupa paksongkong, dodot, tanggai, dan selendang mantri.
Kemudian, seorang penari yang berada di tengah dan paling depan membawa sebuah kotak, yang biasa disebut tepak. Sementara itu, suara gending dari gamelan mengiringi gerak gemulai para penari.
“Baru kali ini, nari pakai dikawal.” Ajeng menyeringai senang. “Bufi, penari yang di depan sendiri membawa apa, sih?” Ajeng penasaran.
“Itu kotak sirih atau tepak, Jeng. Tepaknya berisi daun sirih, kapur, pinang, tembakau, dan gambir.”
“Hah! Buat apa?”
Bufi pun menjelaskan, orang zaman dahulu suka sekali mengunyah daun sirih (nyirih) yang telah diberi berbagai ramuan. Dahulu tepak itu akan diberikan pada tamu kehormatan sebagai ungkapan rasa syukur.
“Ajeng pernah lihat orang nyirih, waktu main ke rumah Eyang di kampung. Tapi, mereka yang nyirih banyakan nenek-nenek, Bufi.”
Ajeng membayangkan nenek-nenek yang nyirih, kemudian mulutnya menjadi merah. Begitu juga saat meludah, ludahnya merah seperti darah.
“Sekarang, kamu lihat gerakan membungkuk dan berlutut itu, mereka juga sesekali melemparkan senyum sambil melentikkan jari-jari kuku. Itu tanda penghormatan pada tamu, Jeng.”
“Orang zaman dahulu begitu beradab dan menghormati tamu, ya, Bufi?”
“Iya, betul. Sebagai generasi penerus bangsa yang beradab, kita harus belajar adab juga. Ingat … utamakan adab, sebelum ilmu.”
Ajeng manggut-manggut mengerti. Sesekali tangannya mengikuti gerak lentik para penari. Hadiah pengetahuan dari Bufi membuatnya bertambah pintar juga bahagia.
Kemudian, Ajeng penasaran dengan jumlah penarinya. Bufi kembali menerangkan, penari yang berjumlah sembilan orang itu menunjukkan jumlah sungai yang ada di Sumatera Selatan.
Bukan hanya gerak tarian yang memikat hati, Ajeng pun terpesona dengan lirik dan nada pada lagu pengiringnya.
“Coba kamu dengar musik dan lirik lagunya, Bufi! Merdu dan penuh penghayatan. Rasanya jadi merinding,” ungkap Ajeng.
“Iya, tarian ini memang istimewa dan hanya diiringi lagu Gending Sriwijaya, lirik dan nadanya punya sejarah panjang yang mengesankan, Jeng.”
“Oya, aku jadi ingin tahu, Bufi. Ayo, ceritakan!” Ajeng tak sabar.
“Baiklah, tapi tunggu ta
rian ini selesai. Akan aku jelaskan seeemuanya!” balas Bufi seraya merentangkan kedua tangan.