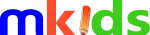Bab 4
Ternyata Mimpi
Kali ini bukan suara Bufi yang Ajeng dengar ketika menutup mata. Namun, suara ….
“Jeng … bangun, Sayang. Ajeng ….”
Seseorang menepuk pundaknya lembut. Sontak dia mengerjap-ngerjapkan mata pelan. Betapa terkejutnya Ajeng setelah menyadari sesuatu. Di hadapannya bukanlah Bufi, melainkan Bunda.
“Bunda?” tanya Ajeng heran.
“Kamu ngapain tidur di kursi taman? Ayo, pulang! Ini udah sore, loh.”
Seketika Ajeng mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ternyata dia masih ada di taman. Begitu menoleh ke arah barat, matanya mendadak silau karena cahaya jingga matahari. Ajeng jadi tahu bila semua yang dilewatinya hanyalah mimpi. Tentu hal tersebut membuatnya kembali sedih dan kecewa.
“Ternyata cuma mimpi,” gumam Ajeng sambil menghela napas.
“Kamu ngomong apa, Sayang?” Bunda mengusap kepala Ajeng.
Ajeng menggeleng. “Bukan apa-apa, Bun.”
“Ayo, pulang. Ini tongkatnya dipakai.”
Ajeng menatap tongkat penyanggah sejenak, kemudian beralih pada kaki yang masih diperban. Semua masih sama, seperti saat dia baru datang ke taman.
Dengan penuh rasa kecewa, Ajeng kembali pulang ke rumah bersama Bunda. Namun, baru beberapa langkah meninggalkan kursi panjang bercat putih, Ajeng seperti mendengar suara Bufi.
Dia pun menengok ke belakang. Tampak seekor kupu-kupu bersayap biru ungu terbang bersama kupu-kupu lainnya. Kupu-kupu cantik itu berputar-putar lalu terbang menghampiri Ajeng. Tiba-tiba si kupu-kupu hinggap di bahu Ajeng.
Suara Bufi begitu pelan, tetapi Ajeng cukup jelas mendengar. “Sampai jumpa lagi, Ajeng.”
“Bufi, kamu benar-benar ada?” bisik Ajeng senang.
“Kamu ngomong sama siapa, Jeng?” tanya Bunda.
Sebenarnya, Ajeng ingin bercerita tentang Bufi, tetapi takut Bunda tak percaya. Ajeng pun memilih untuk merahasiakannya dan langsung mengalihkan pembicaraan.
“Bunda, nanti masak apa buat makan malam?”
“Oh, Bunda masak sayur sup ayam dan perkedel kentang kesukaan kamu, Sayang”
“Asyiiik, pasti enak!” Ajeng bersorak. Dia dapat membayangkan masakan Bunda yang lezat.
Setelah makan malam dan belajar sebentar, Ajeng gegas naik ke ranjang dan merebahkan badan. Belum sempat membaca doa sebelum tidur, Ajeng melihat kupu-kupu bersayap biru ungu masuk melalui lubang ventilasi di atas jendela kamarnya.
Ajeng yang terkejut pun segera bangkit dari ranjang. Masih dengan posisi duduk serta selimut yang menutupi kaki, pandangan Ajeng mengikuti kepakan sayap kupu-kupu itu hingga hinggap di depannya.
“Hai, Ajeng,” sapanya.
Ajeng hafal betul dengan suara Bufi.
“Bufi?” tanya Ajeng gembira.
“Ajeng, kita jadi, kan, ke tempat yang kamu ingin kunjungi?”
“Emang masih bisa?”
“Tentu, sekarang pejamkan mata kamu, Jeng,” pinta Bufi.
Seperti biasa, Ajeng menurut.
Begitu membuka mata, Ajeng sudah berada di tempat yang ingin dikunjungi. Itu terbukti dengan bangunan yang pertama kali dilihatnya adalah rumah Radakng. Rumah itu mirip rumah panggung, tetapi memanjang dan sebagian besar terbuat dari kayu.
“Wah, kita benar-benar sampai di sini, ya, Bufi?”
“Iya, Jeng. Tapi, aku ingin tahu alasan kamu ingin ke tempat ini.”
“Aku sering membaca artikel di koran Ayah, kalau tempat ini menyimpan banyak misteri, juga keindahan. Terutama tariannya, Bufi.”
Ajeng begitu takjub dengan rumah tradisional Suku Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat. Rumah panggungnya unik dan khas. Kemudian, dia mendapati beberapa orang yang jalan berbondong-bondong, baik tua muda, lelaki maupun perempuan pergi ke arah timur.
“Mereka akan ke mana, ya, Bufi?”
Bufi mengangkat kedua bahu. “Entahlah! Mungkin di sana ada pesta.”
“Tunggu ….” Ajeng mendengar suara alunan musik. “Kamu dengar itu, Bufi?”
“Iya, aku dengar.”
Suara itu terdengar samar-samar dan timbul tenggelam karena terbawa angin. Suara itu berasal dari arah yang dituju orang-orang. Ajeng yang penasaran pun, mengikuti mereka dari belakang.
“Ayo, kita ikuti mereka, Bufi. Aku ingin tahu ada apa di sana?”
“Tapi, setahuku orang Dayak itu kasar, Jeng.”
“Tahu dari mana? Ayo, Bufi.”
Ajeng menarik tangan Bufi agar tak ketinggalan jauh dari orang-orang. Tiba di sebuah pelataran luas di depan rumah Radakng terbesar, mereka menjumpai kerumunan orang yang sesak dan ramai.
Suara alat musik suku Dayak Kanayatn pun makin terdengar jelas, seperti Dau (gamelan), Godobokng (gendang), Solekng (suling bambu), dan Agukng.
“Ayo, kita lihat dari dekat, Bufi,” ajak Ajeng.
Baru kali ini, Bufi tak bersemangat. Bufi malah terlihat ketakutan.
“Kamu nggak takut, Jeng?”
Ajeng menggeleng. “Kenapa harus takut?”
Ketika mendekat dan hendak masuk melewati gapura rumah Radakng yang megah, tiba-tiba mereka dihadang oleh dua pria.
“Kalian mau ke mana? Kalian bukan orang suku Dayak Kanayatn, ‘kan?” tanya salah satu yang bertubuh besar.
Ajeng dan Bufi saling memandang. Kemudian, mereka menjelaskan kedatangannya, hanya ingin sekadar melihat.
“Tidak bisa! Kalian tidak bisa masuk, sebelum mendapat persetujuan Sesepuh suku Dayak Kanayatn.”
“Bagaimana ini, Ajeng?” Bufi mengguncang lengan Ajeng.
Ajeng berpikir keras. Dia begitu ingin mengenal kebudayaan Suku Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat. Bila sampai tak diizinkan masuk, dia pasti akan sangat kecewa.