MENCARI BALA BANTUAN
Ega kebingungan.
Untuk sesaat ia hanya berdiri mematung sambil menyendarkan punggung pada sebidang tembok yang berhiaskan patung 5 orang yang menggambarkan kesibukan pekerja perkebunan. Patung itu terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Tembok berpatung itu sekaligus sebagai pintu gapura masuk ke desa Pijiombo.
Sambil menghirup udara dalam-dalam, Ega menatap kosong jalan menikung tajam yang terhampar di hadapannya. Jalan yang sampai sekarang belum tersentuh aspal dan masih berupa jalan berbatu dan berlumpur licin itu biasa disebut warga jalan Kenaren. Ega sendiri tak tahu kenapa disebut seperti itu.
Ega mendesah gundah. Dalam perjalanannya mencari bala bantuan, sedari berangkat dari area perkebunan Sirah Kencong hingga sampai di tanah kelahirannya ini, setidaknya sudah ada tiga orang warga yang ia temui. Ia sudah pula menceritakan segala kejadian yang ia alami bersama Jilan dan Panjul. Namun, tak seorang pun yang mempercayai kata-katanya. Ia dianggap hanya membual.
“Sudahlah Ega, kau nggak usah ngelindur. Hentikan saja bualanmu yang tak berguna itu! Mending segeralah kau pulang dan bantu bapakmu untuk menjaga ternaknya agar tak lagi digondol dan dimangsa harimau hutan,” kata salah seorang warga yang ia temui sambil mencibir.
“Saya tidak sedang menggigau, Pak. Saya mengatakan hal yang sebenarnya,” bantah Ega tak mau kalah.
“Hal yang sebenarnya adalah kau terlalu banyak nonton tivi makanya jadi ngayal ketinggian!” sergah orang itu seraya melangkah pergi.
Tentu saja Ega kesal setengah mati. Dan kekesalan Ega semakin menjadi ketika ia bertemu orang ketiga yang lebih menjengkelkan ucapannya.
“Ega, desa Piiiombo ini adalah desa kecil yang terpencil. Jadi mana mungkin ada komplotan pencuri yang sudai bersembunyi di daerah ini. Saya tahu kok, banyak orang yang telah kehilangan ternaknya seperti dirimu, tapi ya gak perlulah ngarang cerita yang gak masuk akal. Lebih baik berdoa sajalah semoga harimau itu suatu saat bisa ditangkap oleh warga,” kata warga itu secara jelas menyudutkan Ega.
“Tapi Pak semua ini benar adanya!” Ega belum mau menyerah.
“Sudahlah jangan nambah-nambahi masalah yang gak jelas. Semua warga sedang bingung cari cara untuk menangkap harimau pemakan ternak itu. Jadi kalau kau ingin menunjukkan peran, batulah bapakmu jaga keamanan ternak kalian.” Warga itu mengakhiri kalimatnya dengan senyum.
Ega merasa tersudut. Sehabis itu ia tak mau lagi menceritakan tujuan perjalanannya untuk mencari bala bantuan. Bahkan tadi ketika lewat depan Loji, bangunan Belanda yang sudah terbengkalai, sedikit pun ia tak mau menoleh ke sana meskipun ia sempat saksikan banyak warga yang berkumpul di depan bangunan tua yang angker itu.
Ia juga tidak mampir ke rumahnya sebab ia pikir kedua orang tuanya pasti ikut berkumpul di depan Loji itu. Makanya ia langsung menuju ke gapura Pijiombo ini untuk menyusun rencana selanjutnya. Lagi pula ia tak mau membahayakan warga sebab saat di gua tadi ia sempat melihat kalau komplotan pencuri itu memiliki beberapa pucuk senjata api.
“Ah, sepertinya aku harus nekad lapor polisi. Tapi bagaimana caraku ke kantor polisi ya? Mau nebeng orang jelas sudah gak ada yang lewat untuk menuju ke kota kecamatan. Apa aku nekad jalan kaki saja ya? Ah! Rasanya gak mungkin. Kantor polisi terlalu jauh dari sini. Satu setengah jam perjalanan baru sampai. Belum lagi aku harus melewati hutan pinus, hutan karet, serta area perkebunan kopi yang luas dan sepi. Hiiih, takut kan!” pikir Ega semakin bingung saja.
Sejenak matanya memandang ke arah barat. Matahari sudah tenggelam di balik puncak gunung Kelud yang menjulang. Jalan Kenaren yang tadi terhampar jelas di hadapannya, sekarang sudah tak kelihatan lagi bentuknya. Yang tampak hanya hitam dan hitam saja.
Lalu mata Ega beralih ke jalan setapak yang membujur ke timur. Jalan setapak ini merupakan penghubung satu-satunya antara desa Pijiombo dan desa Genjong yang jumlah warganya lebih banyak daripada warga Pijiombo.
“Sepertinya kalau ke kantor polisi lewat Genjong akan lebih memungkinkan. Di sana penduduknya banyak dan jarak ke kecamatan juga lebih singkat. Paling tidak dalam perjalanan aku pasti akan bertemu seseorang yang hendak turun ke kecamatan untuk suatu keperluan. Jadi aku bisa nebeng sampai di kantor polisi tentunya. Ya, inilah satu-satunya yang harus aku lakukan. Kasihan Panjul dan Jilan yang masih berada di gua. Mereka harus segera mendapat bantuan!” pikir Ega sambil memantapkan hati untuk mencari bala bantuan.
Selesai berpikir seperti itu, Ega segera beranjak meninggalkan tempat. Dengan langkah mantap dan penuh keyakinan ia melangkah menyusuri jalan setapak yang biasa dilewati warga Genjong saat berangkat dan pulang mencari rumput untuk pakan ternak.
Dan kini Ega menyusurinya untuk mencari bantuan demi menyelamatkan teman.
***
Pada saat yang sama, Adib terlihat sedang berangkat mengaji ke sebuah surau yang ada di pinggiran dusun Genjong. Dengan gerakan pelan dan santai ia mengayuh sepeda kumbangnya yang telah usang. Seperti biasa sebuah radio kecil juga tergantung di lehernya. Radio yang selalu ada dimanapun Adib berada. Dan radio yang senantiasa menyuarakan lagu dangdut kesukaan orang yang memilikinya.
Sambil bersenandung kecil mengikuti irama lagu yang sedang didengarkannya, sesekali Adib membetulkan bagian lilitan sarungnya yang terasa agak kendor. Sementara gema adzan Magrib sayup-sayup sudah mulai terdengar dari kejauhan.
Saat laju sepedanya sampai di tikungan jalan setapak yang menuju ke desa Pijiombo, tiba-tiba ada seseorang muncul dari mulut jalan. Tak sempat lagi Adib mengerem sepedanya. Dengan gerakan reflek ia berusaha membelokkan arah roda sepeda. Akibatnya …. Bruukk! Roda depan sepeda Adib menyerempet betis orang itu dan berakhir setelah menabrak pagar pekarangan orang. Untung pagar itu terbuat dari bambu, sehingga Adib tak sampai cidera.
Tetapi tak urung Adib terjatuh juga dari sepedanya. Tubuh bongsornya membentur pagar bambu yang langsung jadi miring di beberapa bagian. Tapi Adib tak peduli. Ia segera bangkit dan menghampiri orang yang tak sengaja ditabraknya tadi.
“Maaf! Maaf! Saya gak sengaja. Kau gak apa-apa, kan? Apa kakimu ada yang terluka?” kata Adib cemas. Ia segera membantu orang itu untuk berdiri.
“Saya gak apa-apa. Dan saya yang seharusnya minta maaf karena saya yang menyelonong saja menyeberang jalan,” sahut orang itu.
Sejenak Adib memperhatikan orang itu.
“Bener nih, kamu gak apa-apa?”
Kali ini orang itu hanya mengangguk pelan. Adib semakin penasaran. Firasatnya mengatakan kalau orang di hadapannya ini bukanlah warga desa Genjong. Ia hapal semua orang Genjong. Sekali lagi mata Adib memperhatikan orang itu dengan seksama.
“Iya, aku gak apa-apa. Maafkan aku, ya,” sahut orang itu.
Bersambung …








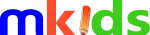



Serasa baca novel serial Astridnya Pak Djokolelono ?
Alhamdulilah, terima kasih. Cerbung ini memang sengaja saya tulis dengan gaya lama seperti kebanyakan buku anak terbitan Balai Pustaka. Saya rindu masa masa di mana perpustakaan menjadi tempat favorit bagi anak anak