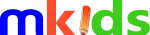.LAYANG-LAYANG PENGIKAT PERSAHABATAN
Tepat pukul 12.15 bel berdentang tujuh kali sebagai pertanda pelajaran telah usai. Dalam sekejap halaman SD Negeri Pijiombo itu sudah dipenuhi oleh anak-anak berseragam putih-merah yang berebut pulang.
Di depan ruang kelas VI, Panjul berjalan pelan-pelan sambil bergurau dengan teman sekelasnya. Saat langkahnya belum lagi sampai di bawah tiang bendera yang berdiri kokoh di pinggir lapangan, Panjul langsung menghentikan langkah ketika terdengar sebuah teriakan yang memanggil namanya.
“Panjul, tungguuu!”
Serta merta Panjul menoleh. Seulas senyum langsung tersungging di bibirnya saat ia mengetahui siapa anak yang memanggilnya. Adib yang sedang berjalan diapit oleh Jilan dan Ega, nampak mempercepat langkah guna menghampiri Panjul.
“Selamat ya Dib, akhirnya kau jadi sekolah di sini juga,” kata Panjul begitu ketiga temannya sudah pada sampai di hadapannya.
“Terima kasih Njul, semua aku lakukan agar kita bisa melakukan petualangan yang lebih seru dari yang kemarin itu,” sahut Adib sambil cengengesan.
“Iya sama-sama. Terus ada apa kau tadi memanggilku?”
“Begini Njul, nanti selesai makan dan istirahat siang, aku tunggu kalian di Jeding Ombo ya,” kata Adib sambil memandang ketiga temannya secara bergantian.
“Buat apa?” Jilan bertanya heran.
“Apa kau mau menantang kami adu sambit layang-layang?” tebak Ega.
“Kalau iya kenapa? Kalian takut?” balik tanya Adib sambil cengar-cengir.
Sejenak Panjul, Jilan, dan Ega saling pandang. Perasaan mereka bergemuruh tak karuan. Semula mereka sangka Adib sudah benar-benar berniat menjalin persahabatan dengan kepindahannya. Tapi nyatanya? Baru sehari pindah sudah pula hendak berulah.
Teringat ejekan sinis Adib saat mengalahkan layang-layang Panjul dulu itu, mereka jadi terpacu semangatnya. Mereka tak ingin mengulang kekalahan yang sama. Untuk itu sesaat mereka saling berbisik dan kemudian menganggukkan kepala.
“Baik, aku terima tantanganmu!” kata Panjul dengan semangat berkobar hebat.
“Nah, itu baru anak hebat!” sahut Adib dengan acungan jempolnya.
Sejenak mereka tertawa bersama-sama.
Tanpa berkata-kata lagi mereka segera melanjutkan langkah. Angin pegunungan yang kencang sesekali menerpa tubuh mereka hingga baju seragam yang mereka kenakan bergerak-gerak tak karuan. Begitu pula rambut mereka yang sudah tak bertopi, nampak terombang-ambing searah dengan laju angin yang belum juga berhenti.
Saat sampai di depan Loji Belanda mereka berhenti sejenak. Menatap halaman Loji yang tadi malam begitu semarak dan ramai, sekarang kembali sepi. Seolah menyimpan sebuah misteri yang membuat bulu kuduk berdiri.
Ngeri!
***
Matahari sudah agak condong ke barat ketika Panjul, Jilan, dan Ega sudah duduk di plesteran semen sisi selatan Jeding Ombo yang terletak di utara Loji. Mereka sama-sama menjuntaikan kedua kaki dan menggoyang-goyangkan kakinya untuk mengusir kejenuhan. Beberapa pencari rumput yang lewat dan melihat mereka hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah bocah itu.
Sesekali Panjul dan Ega melihat ke arah jalan yang membentang di sebelah barat tempat mereka berada guna menyaksikan kalau-kalau Adib sudah nampak. Tapi beberapa kali pula mereka berdua harus kecewa, karena Adib yang diharap kedatangannya belum juga menampakkan batang hidungnya.
Sedangkan Jilan sedari tadi justru hanya menatap gedung sekolahnya yang sepi. Hamparan rumput yang ada di sisi timur halaman sekolah tampak sudah semakin menebal dan meninggi. Padahal baru seminggu ini mereka tidak melaksanakan Jum’at bersih.
Lalu mata Jilan beralih ke gundukan bukit yang ada di sisi barat dan sisi selatan dari gedung sekolah. Dulu bukit-bukit itu masih tampak menghijau karena masih banyak pepohonan yang tegak menjulang. Deretan pohon cengkeh juga masih banyak berdiri subur. Tapi sekarang, hanya tinggal beberapa pohon cengkeh saja yang masih tersisa. Yang lainnya sudah rata dengan tanah. Diganti dengan tanaman rumput yang jelas tak memiliki akar yang cukup kuat untuk menahan tanah dari gempuran air hujan yang sering turun dengan lebat.
Sebenarnya Jilan dan anak-anak lain yang menghuni desa Pijiombo juga sadar apa akibat yang akan ditimbulkan atas perombakan tanaman-tanaman itu. Banjir dan tanah longsor tentunya akan menjadi musibah yang bisa datang kapan saja. Gedung sekolah serta pemukiman warga jelas terancam keamanannya.
Jilan mendesah resah. Dalam lingkar dunia kanak-kanaknya yang masih sempit, sudah dihadapkan pada suatu kondisi yang sulit. Saking terbiasanya mereka bergelut dengan kondisi yang serba kekurangan, membuat bocah-bocah polos itu masih bisa menyunggingkan senyum di antara kekawatiran yang tak pernah terucap.
“Adib mana ya dari tadi kok belum datang-datang?” Suara Panjul memecah kebisuan.
“Atau jangan-jangan Adib telah membohongi kita lagi,” sahut Ega juga mulai cemas. Kecemasan yang cukup beralasan sepertinya.
“Ya gak mungkinlah Adib bohong. Aku yakin dia pasti datang. Kita tunggu saja sebentar lagi,” Jilan berusaha meyakinkan.
Jujur saja meski Jilan selama ini belum begitu mengenal Adib, tapi ia cukuppercaya dengan kesungguhan bongsor itu. Terlebih setelah ia saksikan sendiri pengorbanan Adib yang bersedia bolos mengaji demi untuk mengantar Ega melapor ke kantor polisi. Padahal waktu itu taka da seorangpun yang mau percaya dengan permintaan tiling yang disampaikan Ega. Tapi Adib, sekali mendengar langsung berani bertindak. Bukankah hal itu suatu keberanian dan bentuk kepedulian yang luar biasa?
Hmm, Jilan senyum-senyum sendiri jadinya. Senyum yang membuat kedua temannya jadi saling pandang dan merasa sedikit curiga.
“Kenapa kau malah senyum-senyum sendiri kayak gitu, Jilan?” Panjul bertanya dengan tatapan keheranan.
“Akh, gak ada apa-apa. Aku hanya merasa geli aja dengan kekawatiran kalian,” jawab Jilan dengan pipi merona merah.
“Maksudmu kekawatiranku ini salah, begitu?” Ega sedikit sewot.
“Enggak salah, cuma kekawatiran kalian itu tidak beralasan,” tukas Jilan penuh keyakinan.
Tapi dasar Ega, tetap saja ia ngeyel tak mau kalah sepertibiasanya.
“Tak beralasan bagaimana? Buktinya sampai sekarang Adib belum nongol juga. Iya nggak, Njul?”
“Iya benar, itu,” dukung Panjul kompak.
“Benar apanya? Kalian lihat tuh siapa yang sedang berjalan menuju kemari itu?” bantah Jilan seraya menunjuk ke ujung jalan.
Serentak Panjul dan Ega mengalihkan pandangan ke jalan. Dikiranya Jilan sedang membohongi mereka pula. Tapi ternyata benar saja. Dengan jelas mereka dapat menyaksikan sosok Adib yang sedang berjalan gontai ke arah mereka. Di tangan kanan Adib tampak memegang gulungan benang yang sudah dilumuri ramuan khusus agar tajam saat adu sambit layang-layang. Sedang tangan kirinya menenteng empat buah layang-layang dengan bentuk, ukuran, dan warna kertas yang sama.
Panjul dan Ega jadi geleng-geleng kepala karenanya.
“Iya benar, itu Adib,” gumam Panjul lega.
“Iya itu memang Adib,” kata Ega pula.
“Aku bilang juga apa…,” sahut Jilan sambil menjulurkan lidahnya ke arah Panjul dan Ega yang langsung melengos, membuang muka.
Hehe, Jilan tersenyum kecil melihat tingkah konyol kedua temannya.
Bersambung …