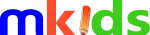Hanya pada setiap Sabtu aku bertemu ayah. Melabuhkan rindu, meruahkan segala keluh-kesah. Ayah bagiku telah menjelma air yang menghilangkan dahaga, ayah adalah hujan yang memberi kehidupan, ayah adalah matahari. Bersama ayah selalu menyenangkan.
Pagi yang beku, aku beranjak dari tempat tidur, mengguyur tubuh dengan air sedingin es. Seketika, aku seperti disergap musim dingin, menusuk sampai ke buku-buku. Aku menggigil tapi tak peduli. Banyak pekerjaan yang harus segera kuselesaiakan.
Sebelum ke sekolah, pekerjaan pertamaku memberi makan ayam yang jumlahnya puluhan. Menyediakan makan kambing-kambing, membantu nenek, dan beberapa pekerjaan rumahan lain. Cukup melelahkan, tapi aku berusaha menikmati semuanya. Dalam kondisi lelah seperti itu, aku akan langsung teringat ayah. Senyumnya, dekapan hangatnya menjadi pengusir segalanya.
Kadang aku merasa kurang beruntung, menjalani hari-hari melelahkan. Aku iri dengan teman sebayaku yang bisa melakukan apa saja. Bangun pagi tanpa beban, berangkat sekolah tanpa penat, pulang sekolah bebas bermain sampai senja tiba. Aku? Pulang sekolah masih harus ke sawah. Menyusuri pematang, di bawah panggang terik matahari, menyabit rumput buat persedian makan kambing-kambing nenek. Lepas itu, saat ashar tiba, aku akan memaksa kaki-kaki lelahku, menyusuri pinggiran sungai, menuju rumah Haji Guru, belajar mengaji hingga magrib tiba. Usai magrib, pulang ke rumah, menyiapkan makan malam, sibuk di dapur, karena berharap sepenuhnya pada nenek tentu tak mungkin. Nenek sudah terlalu renta. Sempurnalah aku jadi pelayan, jadi apa saja, mengerjakan apa saja, termasuk melakoni urusan dapur yang bagi banyak orang hanya pantas bagi tangan anak perempuan.
“Kamu lelaki kuat Raya…!”
Hanya itu jawaban ayah ketika kutanya mengapa aku harus tinggal jauh darinya, menjalani hidup-hidup sulit bersama nenek. Mengapa ayah tidak membawaku bersamanya. Ah ayah, aku selalu tidak pernah tega, jika kudapati dirinya datang membawa buah tangan dari kota, lalu menyerangnya dengan banyak pertanyaan yang mungkin tidak terlalu penting. Kepala ayah sudah terlalu penuh dengan ragam persoalan pekerjaan.
***
Pada Sabtu, saat musim kemarau sudah pergi, mendung menyergap angkasa, menyembunyikan mata hari. Jam pulang sekolah telah tiba, aku mempercepat langkah, tak sabar ingin segera bertemu ayah, berbagi cerita, bertukar kisah. Kilatan petir dan bunyi gemuruh di langit membuat dadaku gaduh. Aku berharap, kali ini hujan tidak turun.
Sampai di rumah, kudapati nenek duduk di atas dipan bambu, menjahit sesuatu. Aku menyalami tangannya, sembari melayangkan pandangan ke segala arah. Sunyi, hanya sesekali bunyi batuk serak nenek dengan matanya yang menunduk, menyelesaikan pekerjaan menjahitnya.
“Nek…! Ayah sudah datang…?”
Pertanyaanku membuat nenek sejenak mengangkat wajahnya, lalu merunduk lagi. Perempuan senja itu kembali sibuk memainkan tangan, melanjutkan pekerjaan. Aku memasang telinga siaga. Tak berani mengulang pekerjaan. Nenek orangnya, sedikit pemarah. Jika usil bertanya, bisa saja amarah tumpah dari mulutnya.
“Baso tadi datang, menyampaikan pesan dari ayahmu. Katanya tak bisa pulang karena harus mengurus pembayaran rekening yang menunggak.
“Ini dari ayahmu Raya, dititp Om Baso…!”
Ah ayah, apa kali ini kau ingkar janji? Aku menerima hadiah itu dengan hati campur-aduk.
“Cepat ganti pakaianmu. Hujan akan turun, lekaslah ke sawah menyabit rumput…!”
Kalimat yang barusan diucapkan nenek, entah mengapa selalu meninggalkan perih di hatiku. Aku tak bisa menyembunyikan kedongkolan, tapi pula tak kuasa membantah. Aku ingat kata-kata Ayah. Aku harus jadi lelaki kuat.
***
Hujan masih malu-malu, rintiknya lemah menyentuh ubun-ubun, aku sudah menyudahi menyabit rumput saat karungku terisi penuh. Sekarung rumput kuangkat dengan susah payah. Aku mirip kuli yang mengangkat sekarung gabah di punggung. Kakiku menjejak, menyusuri pematang yang mulai licin. Dalam kondisi seperti ini, harus ekstra hati-hati karena kaki mudah terpeleset.
Di depan ada titian kecil yang membelah sungai. Aku meniti, tepat saat langkah ketiga, aku kehilangan keseimbangan dan terperosok. Terjatuh ke sungai, menindih hampran air yang mengalir deras. Aku menggapai, meraih apa saja yang bisa menahan derasnya air sungai yang debitnya bertambah karena hujan. Tampak sia-sia, sekarung rumput telah melaju timbul tenggelam, dan aku dalam kondisi yang sama muncul terbenam, kepayahan, berusaha menggapai apa saja. Hujan semakin deras, tiba-tiba aku melihat ayah. Wajahnya sumringah lalu hilang bersama gelap yang tiba-tiba menyerang.
“Raya…!”
***
Kesadaranku belum sempurna saat kurasakan seorang lelaki tiba-tiba mendekapku. Kudapati dadanya bergemuruh. Ayah…!
“Bangun Raya…!”
Samar. Aku mencoba membuka mata, namun sulit. Aku mendengar bunyi sesunggukan yang tegas, juga tangisan merintih dari seseorang yang ringkih. Ayah dan nenek sedang berbagi kesedihan, diikuti banyak orang-orang yang datang. Para tetangga, ada pula teman-teman sekolahku…! Ini dalam rangka apa?
“Bangun Raya…!”
Tapi suara itu makin lirih, lalu seseorang yang lain mendatangiku. Memakai pakaian dari cahaya, cantik sekali. Ibu…? Senyumnya terkulum lalu mendekapku, mengelus kepalaku yang basah oleh air mata. Ibu dari mana? Raya kangen Ibu…? Ah…! Tak ada jawaban, hanya senyumnya yang rekah, lalu melangkah pergi, melambaikan tangan. Aku mengikuti, tapi tiba-tiba tangannya terangkat, memberi isyarat, melarang. Suara semerdu seruling terucap membela telingaku, menggapai hatiku yang selalu bertanya-tanya.
“Raya harus menjaga nenek. Menjaga ayah matahari kita…!”
Gelap, setelahnya semburat warna-warni menyergapku tiba-tiba. Aku melihat ayah, nenek, dan orang-orang yang menyebut di bawah rumah panggung.
“Ada apa…?”
Pertanyaanku menggantung di kolong rumah, hanya dibalas tawa bercampur derai air mata! (*)