Hutan itu terlihat gelap. Rimbun dan rapatnya pepohonan tinggi membuat sinar matahari sulit menembus ke dalamnya. Dedaunan di pucuk-pucuk pohon tertinggi sudah menghalangi sinar matahari menerobos masuk dan menerangi isi hutan. Teduh sekali tampaknya di dalam sana, sekaligus dingin dan lembab. Entah kenapa, suasananya malah terasa tidak menyenangkan. Di tengah cuaca terik seperti ini, seharusnya nikmat berlindung dari sengatan matahari dibawah keteduhan pohon. Tapi tidak di dalam hutan itu. Memasuki hutan itu seolah memasuki gua yang gelap dan panjang tak berujung. Semakin kita berusaha menatap jauh ke dalam hutan, semakin kegelapan yang terlihat.
Hari masih cukup siang. Sinar matahari masih cukup panas membakar kulit. Empat orang anak berdiri diam di ujung jalan setapak, di luar pagar pembatas memasuki hutan. Beberapa pohon rindang di sekitar mereka menaungi mereka dari terik. Tak ada yang bergerak. Keempatnya hanya memandang jauh ke depan.
Di hadapan mereka, hutan gelap berdiri tegak, memanjang dari satu sisi ke sisi terjauh lainnya. Mereka tak dapat melihat ujung hutan ini. Deretan pohon mahoni tua berdiri memanjang di sepanjang tepian hutan, seolah menjadi batas wilayah. Pohon-pohon itu terlihat sudah sangat tua. Tingginya menjulang bermeter-meter menjangkau langit. Pagar kawat penuh karat ikut membatasi tepian hutan ini, berdiri rapuh di bawah deretan pohon mahoni tua itu. Pagar kawat itu tidak kurang dari 2 meter tingginya dan terlihat sudah tua. Di beberapa bagian bahkan tampak sudah bolong dan rapuh dimakan karat. Tak sulit kalau ingin merobohkan kawat pembatas ini. Tapi untuk apa? Siapa yang ingin masuk ke dalam hutan ini?
Angin kencang datang menghembus, menggoyang daun-daun di dahan tertinggi. Suaranya berkeresak memecah suasana yang sedari tadi sunyi. Dari jauh, jeritan monyet liar terdengar melengking tinggi. Jeritan-jeritan lainnya pun terdengar tak lama setelah itu. Lambat laun, jeritan monyet liar terdengar menjauh dan menghilang. Lalu hutan kembali sunyi.
Hutan Larangan itu semakin terasa menakutkan.
Hutan Larangan?
“Kalian yakin kita akan masuk ke dalam hutan ini?” seorang anak memecah sunyi. Dia menatap gugup ke arah hutan, lalu menoleh ke arah tiga orang teman di sampingnya. Anak itu bernama Panca. Dia bertubuh paling kecil di antara tiga orang anak lainnya. Mereka adalah anak-anak dari desa terdekat dengan hutan itu.
Sejenak, tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan itu. Mata ketiganya masih tidak lepas menatap ke dalam hutan. Gelap dan sunyi.
“Apa kalian yakin di dalam sana banyak buah-buahan seperti yang kita bayangkan?” tanya Panca lagi. Dia teringat tujuan mereka ke tempat ini adalah untuk mencari buah-buahan liar di dalam hutan.
“Kalau tidak ada buah-buahan, bagaimana monyet dan binatang lain bisa hidup?” seorang anak bertubuh tinggi langsing menoleh ke arahnya. Dia bernama Jalu. Di sebelahnya, seorang anak dengan wajah yang sangat mirip ikut mengangguk.
“Betul. Monyet-monyet itu pasti akan kelaparan kalau di hutan tidak ada makanan. Mereka pasti akan turun ke kampung untuk mencari makanan. Tapi itu belum pernah terjadi, kan?” timpal Jali, saudara kembar Jalu.
“Bukannya waktu itu pernah monyet-monyet liar menyerbu kampung?” tanya Panca.
“Panca, kejadian itu sudah lamaaaa … sekali. Itupun karena kemarau panjang dan pepohonan mengering. Monyet-monyet itu pasti kekurangan makanan karena pepohonan tidak berbuah. Bukankah beberapa tahun terakhir kita tidak pernah mengalami kekeringan lagi?” Jali mengerling ke arah Panca.
Panca mengangguk gelisah. Dia ingat itu. Kejadiannya sudah lama sekali. Kalau tidak salah, ketika dia masih kelas 2 atau 3 SD. Sekarang dia sudah kelas 6. Berarti hampir 3-4 tahun lalu. “Tapi ….”
“Kamu takut?” tebak Jalu sambil tersenyum.
Panca melirik ke arah Jalu. Raut mukanya tidak menunjukkan bahwa dia memang berani. Sesekali dia bahkan melirik takut ke arah hutan. Dia masih tidak yakin berani memasuki hutan gelap itu. Untuk apa? Banyak kisah-kisah menakutkan yang membuatnya tak pernah berkeinginan masuk ke sana. Sekarang, teman-temannya malah bermaksud pergi ke sana. Apa nggak ada tempat untuk bermain lagi selain ke Hutan Larangan? Keluh Panca dalam hati.
Jalu dan Jali terkikik melihat Panca. Sahabat mereka itu sudah jelas sekali ketakutan sendiri. Bahkan, saat mereka mengajak untuk masuk ke Hutan Larangan, Panca sudah terlihat enggan.
“Hutan Larangan?” Panca ternganga lebar mendengar ajakan Jalu tadi. Di sebelahnya Bima mengerutkan dahinya dalam-dalam. Bima adalah sahabat mereka yang lain. Mereka sedang berkumpul di teras rumah Jalu siang tadi.
Jalu mengangguk sambil nyengir. Dia menatap Panca, Bima, dan juga Jali dengan geli. Dia sudah memperkirakan teman-temannya akan kaget mendengar ajakannya.
“Tapi itu Hutan Larangan, Lu. Kita semua tidak diperbolehkan masuk ke sana,” kata Bima. “Kita mau main apa di sana?”
“Mencari buah-buahan!” teriak Jali. Adik kembar Jalu ini memang pemberani seperti Kakaknya. Mereka berdua memiliki sifat dan karakter yang sama satu sama lain. Karena itu, Jali pun langsung menyetujui usul Jalu untuk pergi ke Hutan Larangan.
“Wah, boleh tuh, Li.” Jalu mengangguk-angguk. Dia tadi asal ngomong aja pergi ke hutan itu, meski belum tahu mau apa mereka ke sana. “Kita mencari buah-buahan liar!”
“Buah-buahan?” kata Panca sambil kemudian mendengus. “Kita bisa memetik buah kersen di halaman rumahku. Ngapain jauh-jauh ke Hutan Larangan?”
“Kersen? Bosan ah. Kita cari buah-buahan lain. Bisa saja di dalam hutan itu banyak buah-buahan yang jarang kita makan. Anggur misalnya. Atau apel.”
Tiba-tiba Bima tertawa ngakak. “Ngarang kamu, Lu. Mana ada di tempat kita buah anggur dan apel? Buah-buahan itu tumbuh di daerah dingin. Daerah kita kan termasuk beriklim panas. Mana cocok buah-buahan itu tumbuh di sini.”
Jalu nyengir. “Siapa tahu aja, Bim,” Jawabnya.
“Atau kita cari nanas hutan. Aku yakin di sana pasti banyak,” timpal Jali.
Panca mendengus lagi. Dia masih tidak mengerti, apa sih mau teman-temannya itu. Buat apa jauh-jauh mencari buah-buahan ke hutan? Hutan Larangan pula.
“Buah Nanas sih di kebun Pamanku juga banyak, Li. Kita bisa minta barang satu buah nanas yang matang.”
“Nggak seru ah kalau minta. Lagipula Pamanmu galak. Salah-salah kita diomelinya pula.” Jali merengut. Dia ingat Pamannya Panca memang terkenal cukup galak. Apalagi terhadap anak-anak yang sering mencuri buah-buahan di kebunnya.
“Sudahlah,” lerai Jalu. “Dari dulu aku ingin sekali masuk ke Hutan Larangan. Aku ingin tahu ada apa di dalamnya, sampai kita dilarang masuk ke sana.”
“Ssshhh … pamali ngomong seperti itu, Lu,” kata Bima mengingatkan. “Sudah banyak cerita yang kita dengar tentang hutan itu. Tidak mungkin orangtua kita melarang kita ke sana kalau memang tidak ada apa-apanya.”
Panca langsung mengangguk cepat.
“Terserahlah. Pokoknya aku ingin ke sana sekarang,” kata Jalu sambil bangkit dari duduknya. “Kalau kalian mau ikut, ikutlah. Kalau tidak, terserah.”
Tanpa memedulikan tatapan protes dari Panca dan Bima, Jalu melangkah ke luar halaman diikuti Jali. Panca dan Bima saling berpandangan sebelum akhirnya mengikuti langkah Jalu dan Jali dengan gontai.
Empat anak tersebut memang bersahabat. Mereka selalu terlihat bermain bersama-sama. Karena itu, meski tidak setuju, Panca dan Bima tetap mengikuti kedua temannya itu.
Sekarang, mereka sudah berada di perbatasan Hutan Larangan. Keempatnya berdiri dengan gamang. Bahkan Jalu dan Jali yang semula tampak berani pun terlihat sedikit ciut. Bagaimanapun, kisah-kisah yang pernah mereka dengar tentang hutan itu cukup membuat buku kuduk mereka merinding.
“Kita duduk dulu. Cape berdiri terus dari tadi,” kata Bima sambil berjalan ke arah pohon kelapa terdekat. Dia lalu duduk di atas tonjolan akar yang menyembul. Bima ini bertubuh tinggi tegap. Rambutnya yang berdiri lurus dipotong pendek mirip tentara. Dibanding yang lain, Bima lebih tenang orangnya.
Jalu, Jali, dan Panca ikut-ikutan duduk di sebelahnya. Pandangan mereka masih tak lepas dari arah Hutan Larangan di depan mereka. Bagi anak-anak itu, Hutan Larangan memang menyimpan banyak tanda tanya. Tidak setiap kali mereka dapat berada sedekat ini. Hutan ini cukup jauh dari desa mereka. Tidak kurang dari satu kilometer jaraknya untuk mencapai pinggiran hutan ini.
“Lebih baik kita pulang saja. Kita nyari belut di sawah atau mandi di sungai.” Panca menggaruk-garuk kepalanya. Dia bosan berdiam diri di tempat itu terus-terusan.
“Menurut kalian, apa benar kisah-kisah yang kita dengar selama ini tentang Hutan Larangan?” tanya Jalu, mengabaikan keluh kesah Panca di sebelahnya.
“Maksudmu?” Bima mengernyit.
“Maksud Jalu, apa kisah-kisah itu benar? Apa bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak-anak saja agar tidak bermain jauh ke tempat seperti itu?” papar Jali sambil menunjuk ke arah hutan. Anak kembar ini sepertinya memang satu pikiran. Apa yang ada di pikiran Jalu, terpikirkan pula oleh Jali. Karena itu mereka sangat cepat saling memahami ucapan masing-masing.
“Kakekku bilang, di dalam hutan itu banyak dihuni hantu dan mahluk-mahluk halus!” kata Panca sambil bergidik. “Hantu-hantu itu tidak segan mengganggu siapa saja yang berani masuk ke wilayah Hutan Larangan.”
“Aku juga mendengar cerita-cerita seperti itu,” ragu Jali mengangguk membenarkan. “Hutan Larangan dipenuhi oleh dedemit.”
“Semua orang pernah mendengar cerita seperti itu.” Bima ikut mengangguk. “Orang-orang yang pernah masuk hutan melihat bayangan-bayangan menyeramkan mengejar mereka.”
“Bang Mamat pernah cerita kalau sebuah bayangan hitam tinggi besar menghadangnya di dalam hutan.” Panca menimpal lagi dengan semangat. Dia ingin Jalu membatalkan niat mereka masuk ke dalam hutan itu.
Jalu mendengus. Dia tidak percaya kalau Bang Mamat yang mengalami kejadian seperti itu. Yang Jalu tahu, Bang Mamat orangnya senang melebih-lebihkan sesuatu. Dia kalau bercerita sering ditambah-tambahi biar terkesan lebih seru. Kalau dia bercerita tentang bayangan seram di dalam hutan, bisa saja itu hanya bayangan sebuah pohon besar, kan? Karena ceritanya ingin terdengar menarik, dia mengarang cerita bahwa bayangan itu adalah sosok mahluk menyeramkan.
“Mau apa Bang Mamat ke Hutan Larangan?” tanya Jalu.
“Katanya mau berburu burung,” jawab Panca.
“Eh, tapi dilarang berburu binatang di Hutan Larangan!” pekik Bima kaget. Siapapun tahu, tidak boleh ada yang mengusik Hutan Larangan dan isinya. Tidak boleh menebang pohonnya, memburu binatangnya, atau merusak isi yang ada di dalamnya.
Panca mengangkat bahu. “Dia sendiri yang bilang begitu.”
“Wah, pantas saja kalau penunggu Hutan Larangan marah. Bang Mamat niatnya jelek sih.” Jali berdecak.
“Kamu percaya Bang Mamat melihat sendiri bayangan seram itu?” Jalu melirik Jali dengan setengah jengkel. Dia Tidak mau adiknya itu malah ikut-ikutan percaya kibulan Bang Mamat.
Jali terdiam seraya nyengir menatap kakaknya. Sementara Panca langsung mengangguk. “Kenapa harus tidak percaya, Lu? Bisa saja Bang Mamat memang melihat bayangan seram itu.”
Jalu mendengus lagi. “Kalian masih ingat ketika dia cerita melihat buaya besar di pinggir sungai? Bang Mamat cerita kalau buaya itu besar sekali dan akan menerkamnya ketika sedang mandi di sungai. Tapi apa buktinya?”
“Seluruh warga kampung tidak berhasil menemukan buaya itu,” kata Bima sambil menahan senyum.
“Yang warga temukan hanya seekor biawak kecil!” timpal Jali sambil tertawa. Ketiga temannya ikut tertawa terbahak-bahak. Mereka masih ingat ketakutan seluruh warga saat mendengar kalau di kampung mereka terdapat buaya besar. Tapi ketakutan itu berubah menjadi kejengkelan karena Bang Mamat berhasil mengelabui mereka.
“Meski begitu, belum tentu cerita-cerita tentang Hutan Larangan itu bohong belaka, Lu,” kata Bima ketika mereka sudah puas terbahak mengingat kejadian konyol beberapa waktu lalu itu. “Dari jaman dulu, kisah tentang Hutan Larangan ini sudah ada.”
Dengan lesu Jalu mengangguk. Dia memang tidak ingin mengabaikan petuah-petuah orangtua tentang Hutan ini. Tapi, dalam hati kecilnya dia selalu penasaran; kenapa orang-orang dilarang memasuki Hutan Larangan ini? Ada apa sebenarnya di dalam hutan yang gelap dan penuh pepohonan ini?
“Tapi kenapa ada beberapa orang yang berani masuk ke dalam hutan itu?” tanya Jali. “Aku sering mendengar ada orang yang mengambil kayu bakar dari dalam hutan itu.”
“Orang-orang tua pasti tahu jampi-jampi untuk masuk ke sana tanpa diganggu penunggu hutan,” tebak Panca. Dia menggeser duduknya, membelakangi hutan. Lama-lama, dia makin seram menatap hutan itu. Apalagi saat itu mereka sedang membicarakan tentang kisah-kisah menyeramkan Hutan Larangan.
“Bisa jadi,” angguk Bima. “Lagipula, hanya orang-orang tertentu yang berani masuk ke sana.”
“Tapi … bukankah kita dilarang mengambil sesuatu dari dalam hutan itu?” tanya Panca lagi. Meski dipenuhi rasa takut, tetap saja dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya.
“Mengambil kayu bakar bukan merusak hutan. Orang-orang hanya mengambil ranting-ranting kering yang sudah terlepas dari pohonnya. Kecuali kalau sengaja menebang pohonnya. Itu yang dilarang,” jawab Jalu.
“Aku rasa Jalu benar.” Jali mengangguk-angguk, mendukung kakaknya.
“Tapi kamu ingin mencari buah-buahan liar di sana!” tiba-tiba Panca teringat kembali rencana Jalu semula. “Itu berarti mengambil sesuatu dari dalam hutan!”
Dalam sekejap Panca merasa bulu kuduknya meremang. Bagaimana kalau penunggu hutan marah?
“Tapi kita kan nggak akan merusak hutan!” elak Jalu. “Kita hanya akan memetik buah-buahan tanpa merusak pohonnya. Lagi pula, kita nggak mungkin memetik seluruh buah yang ada, kan?”
“Buah-buahan itu diperuntukkan untuk monyet dan seluruh binatang yang ada di dalam hutan. Kita akan mencuri dari mereka kalau tetap melakukannya.” Panca tetap ngotot. Sedapat mungkin, dia harus menggagalkan rencana Jalu dan yang lainnya.
Jalu merengut. Rasanya tidak enak juga kalau dianggap mencuri, meski dari seekor monyet liar sekalipun. Keempat anak itu kemudian terdiam. Hanya hembusan angin yang kemudian terdengar menggoyang dedaunan. Suara tonggeret dan lengkingan monyet liar sayup-sayup terdengar jauh dari dalam hutan.
“Eh, kalian ingat nggak cerita yang kita dengar minggu lalu di surau?” tanya Jali tiba-tiba.
“Tentang Kakek-kakek penunggu Hutan Larangan?” tebak Bima.
Jali mengangguk, sementara Panca langsung membuang mukanya. Dia tidak mau mendengar kisah seram lagi.
“Kabarnya banyak orang yang sudah melihat sosok lelaki tua itu,” kata Jali.
“Kakek tua itu mengenakan baju hitam …” gumam Bima.
“ … dan mengenakan topi caping!” imbuh Jalu.
“Kemarin aku mendengar orang-orang di warung membicarakan itu lagi. Katanya sosok Kakek tua itu terlihat di perbatasan hutan dua hari yang lalu,” celoteh Jali sambil merapatkan badan ke arah Kakaknya.
Jalu, Bima, dan Panca terbelalak. Tanpa sadar, mata mereka kemudian sama-sama melirik ke arah perbatasan hutan di depan mereka. Suasana sunyi sekali sekarang. Bahkan suara tonggeret dan jeritan monyet liar tidak terdengar lagi.
“Kakek tua itu terlihat berdiri di dekat rawa, di ujung hutan sebelah sana.” Jali menunjuk ke arah kanannya, ke arah rerimbunan semak tinggi. Di sana memang ada sebuah rawa-rawa yang jarang dilewati orang. Tempat itu berbahaya, karena bukan tidak mungkin orang bisa terperosok ke dalam lumpur dalam kalau mendekatinya.
“Siapa yang bilang begitu?” tanya Jalu.
“Mang Rojak! Katanya, dia sedang mengumpulkan ranting kering untuk kayu bakar di pinggiran hutan.”
“Mang Rojak nggak mungkin bohong. Dia bukan seperti Bang Mamat yang suka mengarang cerita,” kata Bima.
Jalu mengangguk. Dia kenal Mang Rojak, peternak kambing yang rumahnya di ujung kampung. Dia sering menyabit rumput di pinggiran hutan, karena di tempat ini masih banyak rumput untuk kambing-kambingnya.
“Jam berapa Mang Rojak melihat Kakek Tua itu?”
“Katanya sih sore, Lu. Sehabis menyabit rumput, dia masuk ke pinggiran hutan dulu untuk mencari ranting kering.”
Jalu menggaruk-garuk lehernya. Selama ini dia masih sangsi dengan cerita-cerita seperti itu. Hutan Larangan mungkin ada penunggunya, tapi manusia biasa seperti mereka, bukan mahluk-mahluk menyeramkan seperti yang banyak diceritakan.
“Aku tidak percaya ada hantu penunggu Hutan Larangan!” gumam Jalu akhirnya.
Panca dan Bima langsung melotot ke anak itu.
“Hati-hati kamu bicara, Lu!” desis Bima kaget. Matanya melirik ke arah rawa-rawa. “Bagaimana kalau penunggu Hutan Larangan ini dengar?”
“Kamu bisa kualat!” pekik Panca tertahan. Dia merasa bulu tengkuknya langsung berdiri semua. Dia nggak nyangka Jalu akan ngomong seperti itu.
“Kalau tidak ada hantu di sana,” Jali melirik ke arah hutan, “kenapa hutan ini dinamakan Hutan Larangan?” tanyanya ragu. Kali ini dia bingung, apakah harus setuju dengan saudara kembarnya atau tidak. Dia masih teringat obrolan orang-orang tentang Kakek Tua penunggu Hutan Larangan ini kemarin di warung dekat rumah.
“Hutan ini menyimpan sesuatu.” Jalu bergumam lagi. Dia tidak peduli tatapan kaget teman-temannya. Dia hanya memandang jauh ke dalam hutan yang semakin terlihat gelap. Siang sudah turun menuju sore.
“Tidak semata-mata orang-orang tua melarang kita masuk ke dalam sana. Kalau ini hanya hutan biasa, kenapa kita dilarang masuk?” bibir Jalu komat-kamit sendiri.
“Ini bukan hutan biasa, Lu,” pekik Panca. “ini Hutan Larangan!”
“Iya, tapi kenapa harus dinamakan Hutan Larangan?” Jalu menatap Panca. “Kalau sekadar tidak boleh merusak hutan, atau berburu binatang yang ada di dalamnya, kan tidak perlu seperti itu namanya. Hutan lainnya pun namanya tidak seaneh ini.”
Panca menggeram kesal. “Karena hutan ini banyak penunggunya! Bukankah sedari tadi kita membicarakan itu?”
Jalu mendengus.
“Sudahlah, buat apa sih kita mempermasalahkan itu?” lerai Bima. “Yang jelas hutan ini akan tetap menjadi Hutan Larangan. Karena sejak dulu pun sudah begitu namanya. Memangnya kita bisa merubah namanya?” senyum Bima mengembang melihat pertengkaran kecil itu.
Panca dan Jalu merengut.
“Kita jadi masuk ke Hutan Larangan, nggak?” celetuk Jali. “Kalau nggak jadi lebih baik kita pulang saja.”
“Iya, kita ….”
KROSSSAAAKKK!
Suara berkeresak itu menghentikan omongan Panca. Sepertinya ada ranting yang terinjak dan patah, dan … suara itu datang dari arah rawa! Serentak ke empat anak itu menoleh ke arah datangnya suara dengan kaget. Dalam sekejap, wajah keempatnya pucat. Badan mereka langsung menggigil.
Di dekat pagar kawat pembatas hutan, berdiri sesosok tubuh kurus tinggi. Sosok itu berdiri di antara rerimbunan semak tanah rawa. Tubuhnya mengenakan sepasang baju hitam. Di atas kepalanya bertengger topi caping. Yang membuat mereka bergidik, sosok itu berdiri diam menghadap ke arah mereka berempat! Matanya menyorot tajam. Meski jaraknya cukup jauh, tapi mereka melihat mata itu menatap tajam kea rah mereka.
Sosok itu adalah sosok seorang Kakek Tua!
“Hantu penunggu Hutan Larangan!” pekik mereka serentak.
Tanpa aba-aba, Jalu, Jali, Panca, dan Bima membalikkan badannya. Mereka tunggang langgang lari meninggalkan tempat itu, meninggalkan. suara tawa terkekeh-kekeh di belakang mereka.
Hantu penunggu Hutan Larangan ternyata memang ada!








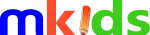



Wah … harus mantengin cerbung ini ?
Terima kasih banyak mba Mia. ^^
Makin dilarang, makin tertantang ini. Go go Jalu, aku mendukungmu! :))
Hahaha … Jalu in action nih. 😀