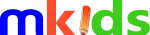“Masih lama nggak sih, Dek!” ucap seorang ibu yang menggendong putra kecilnya.
“Sabar, Bu. Sebentar lagi juga matang, kok.”
“Jangan lelet kalau jualan, memangnya Ibumu kemana?” tanya perempuan itu kesal.
“Ibuku sudah pulang ke kampung-Nya, Bu.”
Awan hitam tiba-tiba muncul. Kondisi cuaca mulai teduh.
“Owh, maksudnya pulang kampung. Kenapa tega ninggalin anak umur sepuluh tahun jualan sendirian, apa nggak khawatir sama anaknya?”
Sabrina tersenyum tipis sambil menahan embun di matanya yang hampir jatuh.
“Maaf bukan ke kampung halaman, Ibu sudah saya pulang ke kampung akhirat.”
Mendengar ucapan gadis malang itu, tiba-tiba butiran bening air jatuh dari pelupuk mata ibu paruh baya itu. Dia sedikit menyesal menanyakan tentang ibu penjual telur gulung.
“Kamu sekarang tinggal sama siapa, Dek?”
“Sama Nenek, Bu.”
“Ya Allah, masih kecil sudah menanggung beban hidup.”
Wanita itu merasa tak tega. Dia menahan sesak di dada sambil mencium ubun-ubun putranya yang sedang tertidur pulas di gendongannya.
“Tidak apa-apa, saya sudah ikhlas, Bu. Sejak kecil saya sudah terbiasa jualan.”
“Ibu salut, deh, sama kamu. Masih kecil, tapi sudah bisa cari duit. Ini ada sedikit uang buat nambahin uang jajan, jangan lupa dibungkus pesanan tadi dan tambah dua lagi, ya.”
“Baik, Bu. Terima kasih.” Jawab Sabrina sambil tersenyum.
Gadis malang itu bernama Sabrina. Seorang anak SD yang dikenal sebagai anak yang tabah. Dia hidup berdua bersama sang nenek. Demi menopang perekonomian hidup, dia rela menjadi penjual telur gulung disela waktu mainnya.
Saat mentari muncul di atas ufuk, Sabrina sudah siap berangkat ke sekolah. Dia tidak membawa tas karena hari ini jadwal pengambilan rapor.
“Jangan lupa bawa titipan dari Nenek, Rin!” teriak Nenek Jamilah dari arah dapur.
“Owh, bungkusan ini. Emang isinya apa, Nek?” tanya anak perempuan itu heran.
“Pokoknya makanan yang paling enak sedunia,”
“Alah, ini, kan cendil, Nek. Kenapa dibilang terenak sedunia?” tanya Sabrina heran. Dia pun menghampiri neneknya sambil berpamitan.
“Karena cendil ini dibuat dengan cinta untuk gurumu. Salam sama Bu Anna, ya. Maafkan Nenek belum bisa ambil rapor ke sekolah. Pinggang nenek sudah encok, jadi nggak bisa jalan jauh-jauh. Mana selama ini kita nggak pernah bisa bayar sekolah, Nenek merasa malu, Rin.”
“Iya, Nek tak apa-apa. Mereka pasti paham sama kondisi kita, jangan merasa malu.”
“Kalau saja waktu itu Ayahmu tidak kawin lagi dan meninggalkanmu di sini, pasti kita masih bisa bayar sekolah.”
“Sudahlah, Nek. Jangan sebut nama Ayah lagi, biarkan dia bahagia tinggal bersama keluarga barunya. Aku tidak apa-apa hidup tanpa Ayah. Toh, tinggal sama Nenek saja, aku sudah bahagia. Kata Ibu guru, hidup ini harus dijalani dengan semangat. Jangan sedih terus, nanti kita jadi orang yang mudah putus asa.”
Nenek tersenyum mengangguk, tapi air matanya mengalir deras.
“Kalau tiba-tiba Nenek sudah tidak bernapas lagi, bagaimana nasibmu nanti?” tanya Nenek cemas.
“Tenang, Nek, ada Allah. Selama kita masih bernapas, Allah pasti nolong kita, aku juga percaya kalau kita berdoa untuk Ibu, pasti dia akan bahagia di akhirat sana. Jangan khawatir, Nek.” Sabrina memeluk sang nenek. Dia mencium tangan neneknya yang sejak tadi bersimbah air mata.
Sabrina mengusap setiap helai rambut sang nenek yang sudah memutih. Kemudian dia memeluknya hangat. Sekarang dia sudah tegar. Wajahnya kelihatan sumringah dan siap berangkat ke sekolah.
Sabrina mengayuh sepedanya dengan kuat agar segera sampai di sekolah, tapi di tengah perjalanan, ada sebuah mobil sedan yang melaju kencang. Mobil berplat Jakarta itu, tiba-tiba menyerempet sepedanya. Hingga membuat Sabrina oleng.
Brakk! Sabrina jatuh di comberan.
“Aduh, kakiku sakit!” Sabrina meringis karena sekujur tubuhnya terasa nyeri. Namun, dia teringat sang nenek yang menunggu di rumah. Jika dia lemah, pasti neneknya akan sedih. Jadi, dia pun segera menghapus air mata yang mengalir di pipi.
Orang-orang yang sedang melewati tempat itu, menarik tangannya. Kemudian, mengangkat sepedanya yang kotor. Seluruh baju Sabrina kena cipratan air keruh di jalan. Termasuk wajahnya. Dia merasa malu dan terpaksa mengurungkan niat berangkat ke sekolah. Apalagi, cendil buatan nenek berjatuhan di tengah jalan bahkan, tak sedikit yang diinjak oleh kendaraan lain.
Di tengah rasa panik, tiba-tiba keluarlah seorang pria dewasa dari dalam mobil.
“Oh, jadi anak ingusan dan sepeda butut ini yang sudah mengahalangi jalanku? Hei, kalau kamu nggak becus naik sepeda, suruh orang tuamu membayar supir untuk mengantarmu kemana-mana. Bukan dengan sepeda butut ini!” teriak lelaki berkulit hitam itu kesal.
“Bukannya minta maaf, Anda malah memarahi saya, apa Anda tidak waras, Pak?”
“Kok, kamu malah nyolot kalau dikasih tahu, jangan sok belagu nanti saya laporkan kamu ke polisi!” ancam lelaki itu dengan sombong.
“Udah, Pak. Nggak usah marah-marah gitu, saya lihat sendiri Anda yang ugal-ugalan di jalan, sekarang kasih ganti rugi sama anak ini.” Balas tukang siomay yang menjadi saksi peristiwa itu.
“Pokoknya saya nggak mau ganti rugi, orang dia yang awalnya menghalangi saya. Mangkanya jadi orang jangan betah hidup miskin.”
Pria berotot itu semakin emosi dan malah menghina Sabrina yang sejak tadi kelihatan shock.
“Eh, Pak. Anak ini, kan hanya lewat, dia pasti tidak sengaja.” Pak Sigit, seorang tukang parkir ikut membela Sabrina.
“Alah, kalian nggak tahu, pasti anak ini nyari cara supaya meras uang orang kaya seperti saya. Eh, bocah! Kamu minta berapa pun, aku nggak mau ganti rugi!”
Mata lelaki itu menatap kedua bola Sabrina dengan tajam. Sementara kedua orang bapak-bapak yang membela Sabrina kelihatan geram.
Wajah sabrina sangat pucat. Dia sangat takut dengan lelaki yang berperawakan tinggi dan jembrosan itu, tapi wajah orang itu mengingatkannya dengan sosok yang dia rindukan selama ini.
Hatinya sedikit berharap bahwa orang itu adalah pria yang selalu datang dalam mimpinya. Saat tengah melamun, tiba-tiba seorang wanita paruh baya berpostur tinggi datang ke tempat itu dengan mengendarai motor. Dia memboncengi seorang nenek tua yang memakai kain larik.
Wajah Sabrina terlihat cerah karena wanita paruh baya itu adalah neneknya.
“Nenek kenapa ke sini?”
“Jangan nanya begitu, Nenek tahu dari Pak Haji kalau kamu ditabrak, jadi langsung minta diantar ke sini sama tetangga. Nenek khawatir, kalau kamu kenapa-napa, Rin.”
“Aku nggak apa-apa, Nek.”
Sabrina menenangkan sang nenek yang setengah panik.
“Syukurlah kamu masih dilindungi Allah.” Nenek memeluk cucunya dengan perasaan lega.
Tiba-tiba lelaki yang menabrak Sabrina dengan lantang bicara.
“Eh, Nenek tua. Ajarin cucu Anda supaya berhati-hati saat naik sepeda di jalan. Jangan sampai tertabrak pengguna kendaraan roda empat.”
Lelaki itu membuka kaca mata hitamnya. Tiba-tiba kedua bola mata sang nenek membelalak. Dia terkejut dan shok karena di hadapannya berdiri sosok lelaki yang tak asing. Begitu pula lelaki itu. Meskipun usianya telah memasuki usia senja, tapi ingatan wanita tua itu masih segar. Dia tidak akan lupa pada sosok lelaki yang telah meninggalkan luka dalam jiwanya beberapa tahun silam.
“Oh, jadi kamu Samsul Bin Ahmad. Kamu yang telah meninggalkan cucuku hidup sebatang kara di dunia ini dan kawin sama janda kaya di kota, berani-beraninya kamu muncul lagi di hadapanku, hah!” Nenek Jamilah naik pitam. Dia tak bisa menahan emosi.
“Astaga, dunia ini terasa sempit rupanya. Aku tak menyangka bertemu lagi denganmu.”
“Jangan banyak omong kamu. Dasar lelaki tidak bertanggung jawab! Yang kamu tabrak ini adalah putrimu sendiri, Samsul.”
“Maksudmu, gadis kecil ini adalah putriku? Ini nggak mungkin terjadi.” Jawab lelaki itu kebingungan. Dia tidak percaya bahwa anak yang dia tabrak tadi adalah putrinya sendiri.
“Sumpah demi Allah, aku nggak pernah rida kamu meninggalkan cucuku. Kamu tidak akan pernah hidup tenang, Samsul!”
Lelaki bernama Samsul itu terperangah. Dia mundur tiga kali. Tubuhnya lunglai, dari raut wajahnya dia kelihatan putus asa dan larut dalam penyesalan.
“Astaga…Maafkan saya, Bu. Waktu itu, saya khilaf.”
“Sekarang, kalau kau tidak mau mengakui putrimu ini tidak apa-apa, biar aku yang urus dia sampai mati, tapi jangan harap kau bisa hidup bahagia. Aku tidak akan memaafkan perbuatanmu, Samsul.” Nenek Jamilah berteriak dengan emosi.
Sabrina pun limbung. Dia tak menyangka bahwa orang yang telah menabraknya adalah ayahnya sendiri. Lelaki yang selama ini selalu datang ke dalam mimpinya. Dia kelihatan sedih, tapi tak berdaya karena tidak bisa berbuat apa-apa.
“Sudahlah, Nek. Jangan emosi, nanti penyakit Nenek kambuh lagi.” Sabrina terlihat cemas.
Sang Nenek tak bisa menahan tangisnya. Dia terisak-isak, seolah-olah melampiaskan amarah yang telah lama dipendam.
“Apakah benar dia ayahku?” tanya Sabrina dengan wajah sedih.
Nenek mengangguk. Dia tak ingin menutupi kenyataan. Cepat atau lambat Sabrina harus tahu wajah sang ayah yang telah lama tak dilihatnya.
Dia mendekati lelaki itu karena sejak bayi dia belum pernah melihat wajahnya. Wajah yang selalu dirindukan dan hadir dalam mimpinya. Sabrina menatap kedua mata Samsul dengan lekat.
Dia menghapus air mata yang sejak tadi membasahi pipi. Lumpur bekas comberan di wajahnya sudah dibersihkan. Hanya ada wajah yang memerah ditiup angin dengan kedua bola mata yang penuh tanya. Sedangkan Samsul hanya diam membisu. Dia terkejut bukan main dan hampir mati lemas karena yang dia maki tadi adalah darah dagingnya sendiri.
Mata lelaki itu memerah bagai saga. Dia mengepalkan kedua tangan ke tanah menyesali perbuatannya. Sekarang dia tak bisa lari dari kenyataan. Sedalam apapun dia ingin melupakan Sabrina, tapi tetap saja riak rindu pada sosok anak perempuan itu selalu mengganggu hidupnya. Saat merunduk karena menahan rasa malu. Tiba-tiba kepala Samsul berputar-putar. Jantungnya berdebar sangat cepat. Hingga akhirnya tubuhnya jatuh ke tanah.
Brakk.
***
Senja datang di peraduan. Sabrina mengayuh sepedanya ke sebuah Musalla dan melaksanakan Salat Magrib, setelah selesai dia kembali pulang. Gadis kecil itu membuka mushaf Al-Qur’an lalu membacanya.
“Faa inna ma’al usri yusra.”
“Inna ma’al usri yusra.”
Sabrina membaca potongan surat Al Insyirah dengan tartil. Suaranya menggema di sudut rumah mungil nan sederhana itu.
Sayup-sayup suara lantunan ayat suci itu, sampai di telinga Samsul. Dalam kondisi pingsan seharian dia mulai tersadar. Tubuhnya yang berotot itu mulai digerakkan pelan-pelan. Kedua bola matanya membuka. Seketika dia mengeluarkan bunyi dari kerongkongan sambil kebingungan.
“Tolong, ada di mana saya? Apakah saya sudah mati?” tanya Samsul sedikit linglung.
Sabrina yang sejak tadi berada di dekat pembaringan Samsul terkejut. Dia lantas mendekati sosok lelaki yang ada dihadapannya.
“Syukurlah kalau kau sudah sadar. Tadi kami menyelamatkanmu saat pingsan di pinggir jalan.”
“Apa? Aku pingsan? Sekarang di mana mobilku?” tanya samsul penuh rasa khawatir.
Saat Sabrina hendak menjawab, tiba-tiba sang nenek datang dan menjawab duluan.
“Tenang saja mobilmu sudah diamankan polisi. Jangan banyak bergerak, Sul. Kau masih lemah.”
Samsul dengan lekat memandang wajah Nenek Jamilah dan Sabrina.
“Kalian berdua yang telah menolongku?” tanya Samsul dengan mata berkaca-kaca.
Sabrina dan Nenek Jamila saling memandang. Mereka tidak menyangka kalau Samsul menyesali semua yang terjadi. Saat itu sikap Samsul terlihat aneh. Bukannya mengucapkan terima kasih, dia malah menangis sejadi-jadinya, dipenuhi rasa penyesalan. Nenek Jamilah berusaha untuk menghiburnya.
“Hei, kenapa kau menangis? Jika kau lapar, aku akan membawakan getuk kesukaanmu. Dulu, waktu Dean masih hidup, kau sering minta dibuatkan getuk, bukan? Tenanglah, jangan mewek terus, tadi Sabrina sudah membuat getuk yang enak.”
Nenek Jamilah menyodorkan piring yang berisi getuk berwarna coklat serta teh hangat.
Samsul tak nafsu makan, dia terlihat murung dan penuh rasa bersalah. Sebab, dia malu mengakui bahwa selama ini dia merindukan Sabrina. Samsul bersikap emosional. Di tengah kondisi tubuh yang masih lemah, dia memaksa bangun dari kasur dan mendekati Sabrina.
“Maaf, Nak. Saya mau bicara empat mata.” Ucap Samsul sambil meraih tangan Sabrina, tapi tiba-tiba Sabrina malah menangkis tangan lelaki itu dan menjauh karena dihantui rasa takut.
“Sudah cukup sampai di situ saja, Pak. Jangan dekati aku karena kau pasti tidak akan sudi dekat dengan anak miskin macam aku, lagi pula aku tidak butuh dikasihani.” Sabrina menunduk. Dia menghapus setiap bulir yang jatuh dari sudut netranya.
Samsul yang terkenal angkuh dan keras kepala itu juga ikut cengeng.
“Apa maksudmu, Nak? Aku ini Ayahmu. Apakah selama ini kau tidak rindu pada Ayah?” tanya Samsul heran.
“Apakah kau lupa, Tuan? Kau sudah meninggalkan aku sejak bayi, jadi aku tidak punya perasaan apapun terhadapmu karena selama ini aku dianggap anak yatim dan aku sudah terbiasa hidup tanpa orang tua. Hanya Nenek satu-satunya orang tuaku. Jadi, kau tak perlu repot-repot mengakuiku sebagai anak.”
Sabrina membuang muka sambil terisak-isak. Dia menahan getir dalam-dalam.
“Maafkan kesalahanku. Aku yang salah karena telah menelantarkan kalian, seharusnya aku tidak bersikap seperti ini. Aku merasa berdosa, tapi aku malu mengakui semuanya. Aku memang lelaki yang tidak bertanggung jawab.” Samsul tak berhenti menangis.
“Sudahlah, Tuan. Aku sudah memaafkanmu. Kurasa Nenek juga. Ya, kan, Nek?”
Nenek Jamilah hanya mengangguk. Tatapannya terlihat kosong dan ikut larut dalam keharuan. Dia memberikan sebuah bingkai merah yang berisi foto seorang wanita yang sedang tersenyum manis.
“Almarhumah Dean pasti bahagia di alam baka, kalau melihat suaminya pulang dan bertemu putrinya. Apa kau tidak rindu dengan dia? Selama setahun dia menunggumu dengan setia, hingga akhirnya dia mengalami sakit parah karena TBC. Dia bekerja siang dan malam tanpa kenal lelah untuk mencari nafkah. Dia berjuang agar kelak punya tabungan pendidikan untuk sabrina.”
Nenek Jamilah terisak-isak. Dia mengenang kembali sosok anak kebanggaannya yang kini sudah tiada.
“Maafkan aku, Bu. Terima kasih sudah menjaga Sabrina.”
“Sekarang sudah terlambat, Tuhan berkehendak lain. Dia meninggal saat putrinya berulang tahun yang keempat.”
Samsul memeluk bingkai foto mantan istrinya dengan emosional.
“Kau harus datang ke pemakamannya dan mendoakannya. Minta maaflah pada dia yang sudah kau sakiti lebih dulu daripada aku dan Sabrina.”
Tangisan Samsul semakin kencang. Dia tak menyangka Tuhan akhirnya mempertemukan dia kembali dengan Sabrina dan membuka tabir masa lalu yang telah lama dia pendam. Dalam kondisi yang masih lemas, Samsul hanya berbaring semalaman. Dia begitu rapuh, hanya memeluk bingkai foto kenangan mendiang istrinya sampai pagi.
Sabrina dan nenek Jamilah tak ingin mengganggu lelaki itu. Kondisi mental Samsul cukup memprihatinkan. Namun, Keesokan harinya dia mulai bangun dan meminta tolong putrinya untuk mengantarkan ke pemakaman -mantan istrinya- Dean.
***
Tepat di depan pusara ibunya, Sabrina mulai mengungkapkan isi hatinya.
“Kau boleh meninggalkan kami di desa ini, pergilah ke kota untuk melanjutkan hidupmu, Tuan.” Kedua mata Sabrina mengembun. Dia merasa tidak pantas menjadi anak Samsul.
“Hey, jangan mengatakan seperti itu, maafkan Ayah, Rin. Kamulah putriku satu-satunya. Jadi, kau harus ikut denganku tinggal di kota.”
“Apa kau sudi menerimaku?” tanya Sabrina dengan tatapan sedih.
“Tentu saja, lihatlah dirimu. Di dalam darahmu telah mengalir darahku. Kau adalah darah dagingku, mana mungkin aku menelantarkanmu lagi. Aku telah menyesali semuanya. Aku berharap kau mau memanggilku dengan sebutan “Ayah.”
Bongkahan air dalam netra Sabrina mengalir deras. Dia mengangguk sambil mengucap kata-kata. “Ayah, aku rindu Ayah.”
Samsul memeluk gadis kecil itu dengan hangat. Dia sangat terharu dan bersyukur akhirnya bisa memeluk buah hati yang selama ini dirindukan.
“Ayah juga kangen, Rin. Ayah janji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ayah akan mengurusmu hingga dewasa.”
Samsul bertekad dalam hati dengan penuh haru. Kemudian, dia mengajak putrinya pulang. Samsul menatap lekat pusara mendiang istrinya. Gundukkan tanah merah itu tiba-tiba disapu angin dan lembut membelai wajahnya dan Sabrina.
Keduanya saling bergandengan tangan. Senyum manis menghiasi wajah mereka.
***
“Janji, ya, Rin. Kasih kabar kalau sudah sampai di kota.”
“Tentu saja, Nek.”
“Kalau kamu rindu, nanti telpon ke Bilqis. Dia akan pinjamkan nenek ponsel katanya.”
“Nenek tenang aja, jangan khawatir. Aku dan ayah pamit dulu, ya.”
Nenek Jamilah terpaksa mengijinkan Sabrina tinggal dengan Samsul di kota. Dia sudah tua dan tidak sanggup membiayai sekolah Sabrina.
“Jaga kesehatan, ya, Bu. Saya akan jaga Sabrina. Di kota dia pasti bisa hidup bahagia. Saya sudah lama bercerai dengan istri kedua, jadi ibu tenang saja. Di sana, Sabrina tidak akan kekurangan suatu apapun karena saya sudah punya pekerjaan tetap.”
“Syukurlah kalau begitu, aku harap kau tidak akan menghianati janji. Aku serahkan Sabrina padamu, jangan pernah menyakitinya walau seujung kuku.” Ucap Nenek Jamilah.
Sabrina dan nenek Jamilah berpelukan erat. Meski berat melepas cucu kesayangannya, tapi dia harus percaya pada Samsul karena sekarang Samsul sudah menerima Sabrina. Hidup harus tetap berlanjut, dia ingin Sabrina menempuh pendidikan sampai sarjana dan terjamin masa depannya, apalagi dia pikir Sabrina akan hidup bahagia bersama sang ayah.
Dalam rasa haru, nenek Jamilah mengantar sang cucu ke mobilnya lalu melambaikan tangan tanda perpisahan. Sementara saat masuk ke dalam mobil, Sabrina masih terisak-isak ketika terakhir kali memandang wajah teduh sang nenek yang telah mengurusnya sejak bayi.
Mobil yang dikendarai Sabrina dan ayahnya melesat jauh meninggalkan desa yang penuh kenangan. Sabrina menepuk-nepuk dadanya. Dia menguatkan hati agar tetap tegar karena dia telah berpisah dengan perempuan yang begitu dicintai, tapi dia juga bahagia karena bisa tinggal dengan sosok ayah yang selama ini dirindukan.
The End