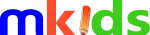Di negeri Haruku, ibu dan bapaknya menghela usia yang tak lama. Laut yang
mendebur deras ombak nan bergulung hanya membuatnya begitu ringkih. Dia yang tak
bertuan menggenapkan usia sendirian. Bertahun-tahun ibunya adalah laut dan bapaknya
adalah ikan. Acara buka sasi¹ yang akan digelar beberapa bulan kemudian tidak lagi menjadi
kebahagiaan pada hatinya. Meski kini dia menjadi salah satu dari kewang², tetapi dia tidak
peduli itu. Tugasnya dilakukan sekadarnya.
Adeo menyisir sungai Learisa Kayeli, menuju tempat sunyi, bukan untuk berjaga-jaga
kalau ada yang melanggar sasi, tetapi untuk menemui orang tuanya yang sudah dulu hidup di
laut: meninggalkan daratan. Dari tepian sungai dihirupnya bau ibunya, dicarinya kenangan
akan bapaknya. Dia duduk di tepian, kakinya menjulur ke bawah, tetapi tidak sampai ke air.
Dipeluknya udara, disusunnya kata-kata kerinduan.
Kematian ibunya bertahun-tahun lalu menyisakan penderitaan panjang pada diri
Adeo. Menjelang acara buka sasi, siapa saja menjadi sibuk. Adeo kecil dan bapaknya pergi
ke kebun belakang rumah untuk mengambil daun kelapa. Mereka rangkai daun itu menjadi
lobe³. Bagi kewang seperti bapaknya, lobe adalah simbol sasi yang penuh dengan pemaknaan
dalam. Di hari-hari itu, semua bahu-membahu dalam mempersiapkan acara buka sasi yang
hanya terjadi satu kali dalam setahun. Beberapa orang memasang tenda dan menderetkan
meja panjang dari Benteng Neuiw Zeelandia sampai sekisar rumah latukeang4
. Meja panjang
itu nanti yang akan digunakan sebagai tempat jamuan makan patita5 yang paling ditunggutunggu oleh semua masyarakat Negeri Haruku.
Siang mulai beranjak menjejak malam. Dengan pakaian serba hitam dan bertelanjang
kaki, latukeang memimpin para kewang berkeliling negeri, menyebut nama teon6 satu per
satu sambil membacakan aturan sasi ikan lompa ke masyarakat untuk menyambut buka sasi
esok hari. Adeo kecil turut bersama bapaknya. Tiga atau empat jam sebelum buka sasi
berlangsung, latukeang dan para kewang membakar lobe di muara sungai. Lobe yang dibakar
adalah sebagai penerang dan penuntun bagi kawanan ikan lompa memasuki sungai. Setelah
itu, orang-orang bersiap memasang bentangan di muara untuk menghalau ikan agar tidak lari
ke laut. Menjelang matahari terbit, seluruh warga berduyun-duyun menuju pesisir sungai
Learisa Kayeli. Di tangan kanan kiri mereka penuh peralatan tangkap ikan.
Setelahnya doa-doa beriringan keluar dari ucapan latukeang, meminta keselamatan. Tangan-tangan kewang yang lain menabuh tifa beberapa kali. Latukeang dan kewang yang
lain pun mulai menebar jala pertama menandai dimulainya sasi ikan lompa. Barulah
setelahnya tifa ditabuh bertalu-talu, semua orang menjatuhkan diri ke sungai. Berbekal jala
maupun ember, ikan-ikan lompa beralih mukim dari sungai ke ember-ember. Itulah hari yang
penuh haru pada diri setiap benak masyarakat Negeri Haruku setelah puasa panjang dari
mencari ikan lompa.
Adeo mengambil posisi bersama teman-temannya. Ember-ember kecil terpasung pada
tangan anak-anak kecil itu untuk diserokkan ke sungai. Begitu mendapatkan panen yang
berlimpah, beberapa kembali ke rumah terlebih dahulu meletakkan hasil tangkapan, beberapa
langsung datang ke acara makan patita. Semua masyarakat Negeri Haruku berbahagia di hari
itu. Adeo membawa satu ember penuh ikan lompa. Adeo dan teman-temannya naik ke tepian
sungai. Dengan perasaan semringah, Adeo beranjak pulang. Dia melihat ayahnya sudah lebih
dulu berjalan menuju rumah. Dia bayangkan ibunya akan memasak kohu-kohu7 kesukaannya. Setelah langkahnya sampai di rumah, semua pikirannya tidak lagi sama. Dari
kejauhan, rumahnya yang biasanya damai berubah menjadi gemeretak pasai. Ayahnya
melongok keluar rumah sambil berteriak-teriak. Adeo yang masih beberapa langkah lagi
menuju rumah, memacu langkahnya. Dilihatnya ibunya tergeletak di ruang tamu dengan mata
terpejam. Adeo kecil tidak tahu apa yang terjadi pada ibunya. Tahu-tahu saja, orang-orang
berbicara tentang kematian ibunya. Tahu-tahu saja, Adeo hanya tinggal bersama ayahnya.
Beberapa tahun setelah itu, Adeo kembali dikejutkan dengan sosok ayahnya yang
kaku pasi di atas kursi pada pagi hari. Adeo yang baru bangun langsung menjerit sejadijadinya. Suaranya memekik ke segala sudut-sudut rumah tetangga, menghantam laut yang
mendeburkan ombak. Suaranya menghambur dengan gema yang memanggil orang-orang
untuk datang ke rumahnya. Adeo tahu, kalau ayahnya sudah mati. Namun, Adeo tidak tahu
mengapa kedua orang tuanya mati begitu cepat dan tanpa pertanda di saat dia masih belia. Berjalan dari tahun-tahun kematian itu, jadilah Adeo yang sekarang duduk di tepian
sungai, menatap tempat yang mengkristalkan kenangan akan kedua orang tuanya. Kini,
setelah lepas semua biduk, lepas pula segala hidupnya yang utuh. Adeo mengutuki diri. Bertahun-tahun dia hidup di situ, sendiri. Hari itu, malam itu, di tepian sungai Learisa Kayeli,
dia merasa benar-benar asing. Dipandanginya air yang mengalir tenang dan bebatuan di
tepian yang berlumut. Dihirupnya dalam-dalam suasana yang mengingatkan pada ikan-ikan
lompa yang berjingkat likat pada saat buka sasi.
Tujuh bulan lalu dia adalah salah satu yang bersuara bersama kewang lain. Mengucap
janji akan menjaga sasi sampai masanya dibuka. Mengencangkan ikat pinggang pada tugas
agungnya. Bulan-bulan berlalu begitu pintas pada kehidupannya yang sendu. Hingga
sampailah pada malam hari itu, dari muara sungai dia dengar dengungan suara-suara khayali
yang memanggil dirinya. Dia tertegun. Pada matanya yang penuh kegetiran, ikan-ikan lompa
terlihat menari-nari, menggiring tubuh Adeo untuk lebih mendekat. Diikutinya suara-suara
yang justru terdengar dari matanya. Telinganya dipenuhi suara-suara tifa yang bertalu-talu
seperti saat akan buka sasi.
Adeo berdiri, mulai melangkah, menyusuri sungai lewat tepian, dan berhenti di
muara. Di tengah-tengah muara sana tertancap tonggak. Tonggak itu terus menggerus
matanya, kepalanya, dan tubuhnya. Tanpa sadar, diceburkannya badannya ke muara itu. Adeo
berputar-putar menantang arus, berenang menuju ke tengah muara bersama ikan-ikan lompa.
Sesekali dia berpikir bahwa ibu bapaknya menjelma menjadi ikan-ikan lompa. Saban tiga
hari sekali, Adeo melakukan ritus itu. Berjalan ke muara, menceburkan diri ke sungai, dan
mengambil beberapa ikan lompa untuk dibawa pulang. Itu menenangkan bagi dirinya. Dia
merasa dengan begitu dia punya teman. Hingga sampailah pada malam itu, sungai Learisa
Kayeli tampak gegap. Riuh suara orang ribut saling sahut paut. Suara orang-orang dan riak
sungai saling berlibat bicara. Sesaat situasi mencekam di dekat muara yang riak airnya
berderai ketika seorang lelaki memegang leher baju Adeo yang wajahnya temaram. “Beta sering lihat waktu masih tutup sasi. Dia ambil ikan lompa,” katanya menggebu- gebu sambil mencengkeram leher baju Adeo.
“Sasi lompa hanya dibuka satu kali dalam setahun, tetapi kalau dirusak, panen kita
jadi tidak banyak. Bagaimana ini, latukeang?” geram lelaki yang lain.
Warga yang lain juga ikut menuduh. Adeo hanya diam dalam cengkeram tangan
lelaki itu. Kepalanya tertunduk lesu. “Sudah! Jangan baribut. Lepas tangan kau, Dawan.” Pecah suara latukeang.
Latukeang berdiri di tengah-tengah mereka yang berseteru. Kemudian diam sejenak. Sesaat, lelaki bernama Dawan melepaskan Adeo. Mereka berdua basah kuyup. Mata Dawan
penuh dengan kemarahan. Baginya, Adeo telah berkhianat atas apa yang telah dipercayakan
kepadanya, yaitu menjaga sasi di sungai Learisa Kayeli. Napas Adeo mulai berat menahan
sesak bicara yang tidak bisa diutarakannya kepada siapa pun. Semua bermula pada suatu malam yang kalut. Berjalanlah lelaki malang—Adeo—
menyusuri tepian sungai Learisa Kayeli. Tanpa disadarinya, tubuhnya terempas masuk di
antara air-air sungai. Dawan yang sedang berjaga pada malam itu dan telah mengamati Adeo
dalam beberapa waktu, tidak segan-segan ikut menceburkan diri ke sungai yang disakralkan
oleh warga Negeri Haruku.
“Muara sungai ini adalah tempat berkembang biaknya ikan lompa. Kita sudah tunggu
lama untuk bisa panen. Namun, ada orang kita yang melanggar. Beta tidak terima kalau bapa
hanya diam saja,” seorang ibu mulai angkat bicara kepada latukeang. Masyarakat di Negeri Haruku begitu menjaga sasi lompa. Tak ada seorang pun yang
berani mengambil ikan di sungai saat masih tutup sasi. Mereka menghargai apa yang telah
menjadi keputusan bersama di negeri itu, sebab sejarah buruk pernah datang ke negeri itu.
Pada suatu masa, tak ada ikan yang bisa dipanen dari sungai maupun laut. Ikan-ikan yang
seharusnya bertumbuh dalam masa yang panjang, agar besar saat waktunya dipanen, sudah
lebih dulu dijaring oleh para pendatang yang biasanya tidak terikat pada adat. Tak jarang juga
perahu-perahu dari perusahaan besar mengambil sumber daya alam di Negeri Haruku.
Perahu-perahu itu menangkap ikan di luar batas mereka. Ketidaktegasan latukeang pada masa
itu pada akhirnya membawa petaka bagi masyarakatnya. Masyarakat Negeri Haruku jatuh
miskin, tangkapan yang didapat oleh masyarakat asli sangat sedikit. Penghasilan sangat
menipis. Mereka menderita. Banyak yang sakit-sakitan dan pada akhirnya meninggal dunia.
Bumi seakan mengutuk Negeri Haruku. Bumi menggelorakan kemarahannya.
Sejak saat itu, masyarakat memberontak. Meminta latukeang yang bertugas untuk
mencari jalan keluar. Akhirnya, adat sasi pun mulai diberlakukan secara tegas. Para kewang
berjaga pada tempat-tempat yang diberlakukan sasi pada saat tutup sasi. Perlahan tetapi pasti,
masyarakat mulai mendapatkan hasil sumber daya dari alam sekitar yang berkualitas. Sangat
jarang bahkan hampir tidak pernah terjadi ada masyarakat yang melanggar sasi. Namun, di hari ini, entah bagaimana, masyarakat Negeri Haruku digemparkan oleh
Adeo yang melanggar sasi. Adeo hanya bisa menginsafi dirinya saat semua orang
menggiringnya ke rumah latukeang. Di rumah itu, Adeo dan Dawan didudukkan pada sebuah
kursi bersebelahan. Dimintanya dari latukeang agar dirinya menjelaskan apakah persaksian
Dawan benar adanya. Orang-orang itu ramai, turut serta berkumpul di rumah latukeang. Adeo
yang malang, penjelasannya mungkin tak bisa diterima orang. Dia memilih mengangguk dan
terdiam tanpa sepatah kata untuk menjelaskan. Kepalanya tegak, pandangannya lurus ke
depan, tetapi kosong. Ketika latukeang memberinya kesempatan untuk berbicara, dia
menolak. Latukeang menarik napas panjang. Matanya mengisyaratkan kesedihan pada salah
satu kewang yang paling dipercaya. “Adeo…” mulutnya membuka.
“Saya tidak tahu apakah roh-roh tete nene moyang kita akan menghukummu, seperti
mereka menghukum ayah ibumu. Atau mungkin kesendirianmu saat ini adalah hukuman dari
roh-roh tete nene moyang untukmu karena kamu mengulangi perbuatan kedua orang tuamu
dahulu. Namun, sebagai latukeang, saya harus menegakkan hukum yang adil bagi siapa pun,”
ucap latukeang. Adeo justru terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh latukeang bahwa
kematian kedua orang tuanya adalah hukuman dari roh-roh moyang mereka. Adeo semakin
tidak bisa berpikir apa-apa. Tak pernah ada sebelumnya, orang yang mengatakan begitu
kepadanya. Sama sekali tak ada. Adeo berpikir mungkin benar apa yang dikatakan latukeang
kepadanya bahwa kesendiriannya selama ini adalah salah satu dari hukuman itu. Orang-orang
juga baru tahu akan hal itu. Mereka menggeleng-gelengkan kepala melihati Adeo.
Setelah diskusi panjang dalam dua pekan, latukeang bersama kewang lainnya
memutuskan hukum cambuk bagi Adeo. Sanksi denda tak akan bisa dibayarnya, kerja paksa
apalagi. Hari-hari Adeo hanya dipenuhi dengan lamunan-lamunan panjang. Lamunan tentang
orang tuanya, tentang masa kecilnya. Dia terus melamun. Tanpa bekerja, tanpa pergi ke
mana-mana. Setelah dilepas sandang kewang dari dirinya, Adeo menghabiskan sisa hidupnya
di rumah sampai pada hari penghukuman itu. Pintu rumahnya selalu tertutup dan tidak pernah
ada yang mengetuk sampai latukeang bersama beberapa kewang lain datang. Dia mengetuk
pintu rumah Adeo. Satu kali, tidak ada jawaban. Dua kali, tiga kali, tetap tidak ada jawaban.
Akhirya, mereka membuka paksa pintu itu.
Dengan sangat terkejutnya latukeang mendapati Adeo yang tergeletak pucat di lantai.
Bau busuk sudah semerbak menyelimuti badan Adeo. Adeo telah mati. Tak ada yang
mengerti mengapa bisa terjadi. Hari yang seharusnya digunakan sebagai hari penghukuman
bagi Adeo justru beralih menjadi hari upacara penguburan bagi dirinya. Semua warga Negeri
Haruku kemudian berkumpul untuk membantu upacara penguburan tersebut. Mereka tidak
menyangka bahwa nasib satu keluarga Adeo berakhir sama.
“Saat kita akan menghukum Adeo, roh-roh tete nene moyang lebih dulu
menghukumnya,” pungkas latukeang pada upacara pemakaman itu.
Catatan:
1. Sasi: larangan sementara untuk tidak mengambil hasil sumber daya alam sekitar.
2. Kewang: kelompok yang mengawasi sasi.
3. Lobe: obor dari daun kelapa.
4. Latukeang: pimpinan kewang yang mengawasi keberjalanan sasi.
5. Makan patita: acara makan bersama dengan suguhan makanan tradisional khas.
6. Teon: nama asli kampung.
7. Kohu-kohu: makanan tradisional khas Maluku yang terbuat dari ikan lompa yang
ditumbuk halus dan dicampur dengan kelapa parut.
Identitas Penulis
Nama lengkap : Afifah Nada Putri Ramadhani
ID Instgram : @cangkirblirik
Nomer WA : 085802528943
Email : nadaputri823@gmail.com