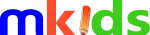Naik, naik, naik lebih tinggi.
Aku suka memandang jalan dari sini.
Lihat! Tukang sayur memanggil pembeli.
Tetanggaku, Pak RT sedang menyiram bunga sambil bernyanyi.
Hihi … suaranya terdengar sampai sini.
“Loh, Putri! Awas jatuh. Sini, bantu Bapak merawat bunga.” Pak RT tiba-tiba menengadah, melihatku dari bawah.
Aduh, haruskah aku sembunyi?
Kurendahkan badan, diam di atas batang paling besar.
“Putri! Ayo lekas turun!” Yang Itu suara Ibu.
“Bantu Ibu memasak!” Ibu berteriak sekali lagi.
Aku tidak suka memasak.
Mengupas bawang, memotong kentang.
Merebus telur, menumis sayur.
Berdiri di depan kompor,
rasanya seperti dalam oven.
“Putriiiii!!” Suara Ibu terdengar kesal.
Secepat tupai aku turun.
“Bolehkah aku cuci piring saja?” tawarku.
Tanpa menunggu jawaban Ibu,
aku buru-buru mengambil sabun.
Main air lebih menyenangkan,
daripada memotong kentang!
“Lihat Putri, gaun ini cantik sekali. Merah muda kesukaanmu. Seperti putri!”
Ibu menunjuk gambar majalah.
Aku suka merah muda, tapi tak suka gaun berenda.
Celana merah muda juga cantik.
Atau kaus pink yang berbintik-bintik.
“Belajar menari, yuk. Anggun, berlenggak-lenggok seperti putri Jawa,” ajak Ibu.
Aduh Ibu, bolehkah aku memukul gamelan saja?
Menarikan pemukul di atas bonang.
Pasti lebih menantang!
Hari minggu selalu yang paling ditunggu.
Aku bisa bersepeda, kadang-kadang berseluncur dengan sepatu roda.
Atau hanya lari keliling stadion saja.
Minggu ini ada yang berbeda.
Di halaman stadion ada dinding, dengan tempelan batu warna-warni.
Satu pendek. Satu lagi lebih tinggi.
“Untuk olahraga panjat dinding,” kata Ayah.
“Wah, aku mau mencoba!” seruku.
Panjat pohon sudah biasa, panjat dinding pastinya aku suka!
Kuminta Ayah bertanya kepada pelatih.
“Untuk anak-anak, dinding yang lebih pendek. Tidak bisa langsung memanjat. Harus latihan dulu,” jelas Ayah.
“Tidak apa-apa, Ayah. Aku akan giat latihan.” Tekadku sudah bulat.
Olahraga panjat dinding perlu peralatan khusus.
Helm, pelindung siku dan lutut, juga sepatu lentur.
“Apa tidak berbahaya? Ada temanmu yang iku?” Ibu cemas.
“Aman, kok, Bu. Ada tali pengaman. Anak-anak diawasi pelatih tiap memanjat.” Ayah menenangkan.
“Teman sekolah? enggak ada. Memanjat kan, hanya butuh kaki. Nanti dapat teman baru ,” timpalku mantap.
Aku giat berlatih.
Pemanasan, bergelantungan, menguatkan dan melenturkan
otot kaki dan lengan.
Panjat dinding berbeda dengan memanjat pohon.
Tidak ada batang untuk diraih dan dipijak, digantikan batu buatan.
Tidak bisa sembarangan menapak, sesuaikan dengan kekuatan kaki.
Tidak bisa sembarangan pegangan, sesuaikan dengan kekuatan lengan dan jari.
Lebam dan memar menghiasi.
Siku, lutut, juga tungkai kaki.
Karena aku jatuh dari gantungan, juga tidak fokus waktu pemanasan.
Dua minggu kemudian aku diperbolehkan memanjat.
Hatiku berdebar campur tidak sabar.
Helm merah muda, pengaman dan sepatu sudah siap.
Dengan semangat aku memanjat.
Mengayun lengan, kaki mencari pijakan, menahan beban badan.
Di separuh tinggi dinding, aku tergelincir.
Pegangan terlepas, aku meluncur.
Secepat kilat aku mengayun, meraih batu terdekat.
Kaki membentur dinding. Aku meringis, sakitnya menembus pelindung lutut.
Namun aku bertahan.
Pelan-pelan mencari pijakan.
“Tarik napas panjang, lalu lanjutkan.” Pesan pelatih terngiang-ngiang.
Semangatku kembali lagi.
Sedikit-sedikit, naik.
Meraba, mengayun di pegangan terakhir.
Akhirnya aku berhasil!
Kutinju udara, kuacungkan helm merah muda.
Senangnya seperti mencapai puncak dunia!